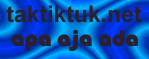Oleh: Bambang Budi Utomo*
Jikalau engkau ingati sungguh,
Angin yang keras menjadi teduh,
Tambahan selalu tetap yang cabuh,
Selamat engkau ke pulau itu berlabuh.
(Hamzah Fansuri, Syair Perahu).
Angin yang keras menjadi teduh,
Tambahan selalu tetap yang cabuh,
Selamat engkau ke pulau itu berlabuh.
(Hamzah Fansuri, Syair Perahu).
Abstrak:
Sejak abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, kawasan Asia Tenggara mulai berkenalanan dengan “tradisi” Islam, meskipun frekuensinya tidak terlalu besar. Pengenalan ini berlangsung sejalan dengan munculnya para saudagar Muslim di beberapa tempat di Asia Tenggara. Bukti tertua adanya “komunitas” Muslim di Asia Tenggara adalah dua buah makam yang bertarikh sekitar abad ke-5 Hijriah/ke-11 Masehi di Pandurangga (kini Panrang, Viet Nam) dan di Leran (Gresik, Indonesia).
Kehadiran Islam secara lebih nyata di Indonesia terjadi pada sekitar abad ke-13 Masehi, yaitu dengan adanya makam dari Sultan Malik as-Saleh yang mangkat pada bulan Ramadhan 696 Hijriah/1297 Masehi. Ini berarti bahwa pada abad ke-13 Masehi di Nusantara sudah ada institusi kerajaan yang bercorak Islam.
Para saudagar Muslim sudah melakukan aktivitas dagangnya sejak abad ke-7 Masehi. Beberapa kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara sudah melakukan hubungan dagang dan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah. Bukti-bukti arkeologis yang mendukung ke arah itu ditemukan di Laut Jawa dekat Cirebon. Di antara komoditi perdagangan yang asalnya dari Timur Tengah ditemukan indikator “keislaman” yang berupa sebuah cetakan tangkup (mould) yang bertulisan asma’ul husnah.
Meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia menganut paham Sunni, namun pada prakteknya saat ini di Sumatra dan Jawa menganut paham Syi’ah. Data arkeologis menunjukkan bahwa Islam yang masuk ke Nusantara berasal dari Persia melalui Gujarat, kemudian dibawa oleh para saudagar ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Semenanjung Tanah Melayu.
Kata kunci: Perdagangan, Persia, kufik, Syi’ah, tradisi Syi’ah
Pengantar
Berbicara tentang Islamisasi di Nusantara, pertanyaan kita adalah bilamana Islam masuk ke Nusantara dan siapa yang membawa atau menyebarkannya. Pertanyaan kemudian, Islam seperti apa yang masuk dan bagaimana bentuknya yang sekarang? Pertanyaan pertama dan kedua dapat dijawab secara teoritis melalui bukti-bukti arkeologi mutakhir yang sampai kepada kita, sedangkan pertanyaan berikutnya dapat dijawab melalui kacamata budaya yang masih dapat disaksikan di beberapa tempat di Nusantara.
Hingga saat ini tidak ada satupun bukti tertulis yang secara tersurat menyatakan bahwa Islam masuk di Nusantara pada tahun atau abad sekian dan yang membawa masuk adalah si Nasruddin (misalnya). Kajian mengenai dugaan masuknya Islam di Nusantara hingga saat ini baru didasarkan atas bukti tertulis dari nisan kubur serta beberapa naskah yang menuliskan para pedagang Islam yang ditemukan di beberapa tempat di Nusantara, seperti di Aceh, Barus (pantai barat Sumatra Utara) dan Gresik (Jawa Timur).
Islamisasi di Nusantara erat kaitannya dengan sejarah Islam yang hingga kini penulisannya belum “lengkap” dan sifatnya masih parsial. Keadaan seperti ini jauh-jauh hari sudah disinyalir oleh Presiden Soekarno yang menyatakan bahwa sikap ulama Indonesia kurang atau bahkan tidak memiliki pengertian perlunya penulisan sejarah. Di samping sikap ulama Indonesia tersebut, masih ada kendala lain untuk menuliskan sejarah. Kendala itu antara lain kurangnya data atau sumber-sumber tertulis, serta luasnya geografis Indonesia sehingga untuk mengintegrasikan data dari berbagai daerah juga sulit.
Mengenai darimana Islam masuk Nusantara, ada beberapa pendapat dengan argumennya masing-masing. Ada yang berteori bahwa Islam datang dari Arab, Persia, India, bahkan ada yang menyatakan dari Tiongkok. Meskipun pendapat mengenai asalnya Islam berbeda-beda, namun ada kesamaan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui “perantaraan” kaum saudagar. Mereka berniaga sambil menyebarkan syi’ar Islam. Hal ini sesuai dengan Hadist: “Sampaikanlah dari saya ini walau hanya satu ayat”. Kemudian sesampainya di Nusantara, barulah disebarkan oleh ulama-ulama lokal atau para wali seperti di Tanah Jawa ada Wali Songo.
Tidak ada satupun pendapat yang pasti mengenai kapan masuknya Islam di Nusantara jika mengingat hubungan kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan Timur Tengah, Persia, India, dan Tiongkok sudah berlangsung lama. Para saudagar dari tempat-tempat tersebut membawa dan mengambil komoditi perdagangan dari dan ke Nusantara. Dari Nusantara mereka membawa hasil-hasil hutan yang laku dijual di pasaran, seperti kapur barus, kemenyan, dan rempah-rempah. Dari tempat asalnya mereka membawa barang-barang kaca, keramik, kain sutra/brokat, batu-batu mulia dan barang-barang perunggu. Sebelum Islam ada, para pedagang, pendeta, dan bhiksu menyebarkan budaya India di Nusantara, termasuk penyebaran agama Hindu dan Buddha. Pada masa abad ke-7-10 Masehi, Śrīwijaya pernah menjadi pusat pengajaran agama Buddha. Dengan demikian, kuat dugaan bahwa Islam masuk ke Nusantara juga dibawa oleh para saudagar.
Baru-baru ini, sektar tahun 2004 di perairan laut Jawa sebelah utara Cirebon ditemukan runtuhan sebuah kapal yang diduga tenggelam karena kelebihan muatan. Berdasarkan pertanggalan keramik dan teknologi pembuatannya, kapal yang tenggelam tersebut berasal dari sekitar abad ke-10 Masehi. Muatannya bermacam-macam yang berasal dari berbagai tempat di luar Nusantara. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, dapat diduga bahwa barang-barang muatan kapal tersebut berasal dari daerah Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Sebagian besar merupakan barang dagangan, dan sebagaian lagi merupakan barang-barang untuk upacara keagamaan atau benda-benda keagamaan.
Dalam tulisan singkat ini, saya hendak mengungkapkan tentang salah satu cara masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara pada satu kurun waktu sekitar abad ke-10 Masehi. Data untuk bahan kajian berasal dari artefak-artefak yang ditemukan dari kapal yang tenggelam di perairan Cirebon serta data lain yang ditemukan dari hasil penelitian arkeologi. Dari data tersebut kemudian akan ditarik pada budaya Islam di Nusantara dalam konteks kekinian. Timbul dan berkembangnya suatu aliran atau mazhab tertentu dapat tergantung darimana asalnya aliran tersebut. Pada masa kini, sebagian masyarakat yang beragama Islam di Indonesia menganut tradisi Suni. Namun tidak tertutup kemungkinan ada juga yang menganut tradisi Syi’ah. Kedua tradisi tersebut bermazhab Syafi’i.
1. Pelayaran dan Perdagangan
Sumber-sumber tertulis (sejarah) yang merupakan catatan harian dari orang-orang Tionghoa, Arab, India, dan Persia menginformasikan pada kita bahwa tumbuh dan berkembangnya pelayaran dan perdagangan melalui laut antara Teluk Persia dengan Tiongkok sejak abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah, disebabkan karena dorongan pertumbuhan dan perkembangan imporium-imporium besar di ujung barat dan ujung timur benua Asia. Di ujung barat terdapat emporium Muslim di bawah kekuasaan Khalifah Bani Umayyah (660-749 Masehi) kemudian Bani Abbasiyah (750-870 Masehi). Di ujung timur Asia terdapat kekaisaran Tiongkok di bawah kekuasaan Dinasti T’ang (618-907 Masehi). Kedua emporium itu mungkin yang mendorong majunya pelayaran dan perdagangan Asia, tetapi jangan dilupakan peranan Śrīwijaya sebagai sebuah emporium yang menguasai Selat Melaka pada abad ke-7-11 Masehi. Emporium ini merupakan kerajaan maritim yang menitik beratkan pada pengembangan pelayaran dan perdagangan.
Nama Persia yang sekarang disebut Iran, menurut catatan harian Tionghoa adalah Po-sse atau Po-ssu yang biasa diidentifikasikan atau dikaitkan dengan kapal-kapal Persia, dan sering pula diceriterakan sama-sama dengan sebutan Ta-shih atau Ta-shih K’uo yang biasa diidentifikasikan dengan Arab. Po-sse dapat juga dimaksudkan dengan orang-orang Persia yaitu orang-orang Zoroaster yang berbicara dalam bahasa Persi –orang-orang Muslim asli Iran—yang dapat pula digolongkan pada orang-orang yang disebut Ta-shih atau orang-orang Arab. Orang Zoroaster dikenal oleh orang Arab sebagai orang Majus yang merupakan mayoritas penduduk Iran setelah pengislaman.
Kehadiran orang-orang Po-ssu bersama-sama dengan orang-orang Ta-shih di bandar-bandar sepanjang tepian Selat Melaka, pantai barat Sumatera, dan pantai timur Semenanjung Tanah Melayu sampai ke pesisir Laut Tiongkok Selatan diketahui sejak abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Mereka dikenal sebagai pedagang dan pelaut ulung. Sebuah catatan harian Tionghoa yang menceriterakan perjalanan pendeta Buddha I-tsing tahun 671 Masehi dengan menumpang kapal Po-sse dari Kanton ke arah selatan, yaitu ke Fo-shih (Śrīwijaya). Catatan harian itu mengindikasikan kehadiran orang-orang Persia di bandar-bandar di pesisir laut Tiongkok Selatan dan Nusantara. Kemudian pada tahun 717 Masehi diberitakan pula tentang kapal-kapal India yang berlayar dari Srilanka ke Śrīwijaya dengan diiringi 35 kapal Po-sse. Tetapi pada tahun 720 Masehi kembali lagi ke Kanton karena kebanyakan dari kapal-kapal tersebut mengalami kerusakan.
Hubungan pelayaran dan perdagangan antara bangsa Arab, Persia, dan Śrīwijaya rupa-rupanya dibarengi dengan hubungan persahabatan di antara kerajaan-kerajaan di kawasan yang berhubungan dagang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya beberapa surat dari Mahārāja Śrīwijaya yang dikirimkan melalui utusan kepada Khalifah Umar ibn ‘Abd. Al-Aziz (717-720 Masehi). Isi surat tersebut antara lain tentang pemberian hadiah sebagai tanda persahabatan.
Bukti-bukti arkeologis yang mengindikasikan kehadiran pedagang Po-sse di Nusantara (Śrīwijaya dan Mālayu) adalah ditemukannya artefak dari gelas dan kaca berbentuk vas, botol, jambangan dll di Situs Barus (pantai barat Sumatera Utara) dan situs-situs di pantai timur Jambi (Muara Jambi, Muara Sabak, Lambur). Barang-barang tersebut merupakan komoditi penting yang didatangkan dari Persia atau Timur Tengah dengan pelabuhan-pelabuhannya antara lain Siraf, Musqat, Basra, Kufah, Wasit, al-Ubulla, Kish, dan Oman. Dari Nusantara para pedagang tersebut membawa hasil bumi dan hasil hutan. Hasil hutan yang sangat digemari pada masa itu adalah kemenyan dan kapur barus.
Hubungan pelayaran dan perdagangan yang kemudian dilanjutkan dengan hubungan politik, pada masa yang kemudian menimbulkan proses islamisasi. Dari proses islamisasi ini pada abad ke-13 Masehi kemudian muncul kerajaan Islam Samudera Pasai dengan sultannya yang pertama adalah Malik as-Saleh yang mangkat pada tahun 1297 Masehi. Menurut kitab Sejarah Melayu, Hikayat Raja-raja Pasai, dan catatan harian Marco Polo yang singgah di Peurlak tahun 1292 Masehi, Samudera Pasai bukan hanya kerajaan Islam pertama di Nusantara, tetapi juga di Asia Tenggara. Kehadiran kerajaan Islam ini semakin mempererat hubungan antara Sumatera dan negara-negara di Arab dan Persia.
Pada pertengahan abad ke-14 Masehi Ibn Batuta singgah di Pasai yang pada waktu itu diperintah oleh Sultan Malik al-Zahir. Dalam catatan hariannya disebutkan bahwa Sultan adalah seorang penganut Islam yang taat dan ia dikelilingi oleh para ulama dan dua orang Persia yang terkenal, yaitu Qadi Sharif Amir Sayyid dari Shiraz dan Taj ad-Din dari Isfahan. Ahli-ahli tasawwuf atau kaum sufi yang datang ke Samudera Pasai dan juga ke Melaka dimana para sultan menyukai ajaran “manusia sempurna/Insan al-Kamil” mungkin sekali dari Persia.
Beberapa ratus tahun sebelum Kesultanan Samudera Pasai, di wilayah Aceh sudah ada kerajaan yang bercorak Islam, yaitu Kerajaan Peurlak. Kerajaan ini berdiri pada tahun 225 Hijriah atau 845 Masehi dengan rajanya Sultan Sayid Maulana Abdal-Aziz Syah keturunan Arab-Quraisy yang berpaham Syi’ah.
Tingginya intensitas hubungan perdagangan antara Persia dan kerajaan di Nusantara demikian tinggi. Tidak mustahil di beberapa tempat yang dikunjungi pedagang Persia, tinggal dan menetap pula orang-orang Persia. Di tempat ini timbul juga kontak budaya antar dua budaya yang berbeda, dan tidak mustahil ada juga penganut Islam Syi’ah. Hal ini dapat dideteksi dari adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh kaum Syi’ah.
2. Tinggalan Budaya
Pada sekitar abad ke-7 Masehi para pedagang Muslim dari Timur Tengah dan Persia giat melakukan aktivitas perdagangan. Berdasarkan suatu keyakinan bahwa setiap insan dalam pandangan Islam termasuk pedagang Muslim mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ajaran Islam kepada siapapun sesuai dengan cara yang baik dan persuasif, sejalan dengan urusan perdagangan menyebar pula agama Islam. Berawal dari pengislaman daerah pesisir Anak Benua India, kemudian memicu/merangsang bukan saja hubungan dagang tetapi juga berbagai bentuk hubungan dan pertukaran keagamaan, sosial, politik, dan kebudayaan. Sebenarnya sejak abad-abad pertama terjadinya perdagangan internasional melalui laut, bukan hubungan perdagangan semata, tetapi juga hubungan politik dan kebudayaan.
Meskipun menganut mazhab yang berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia (Sunnah wal Jamaah mazhab Syafi’i), bangsa Persia sedikit banyak telah berjasa dalam penyebaran dan pengembangan Islam di Nusantara. Hal ini terbukti dengan tinggalan budayanya baik yang berupa kebendaan (tangible), maupun yang bukan (intangible). Tinggalan budaya tersebut masih dapat ditemukan di berbagai tempat di Nusantara, terutama di nusantara sebelah barat, seperti di Sumatera dan Jawa.
2.1 Kargo Cirebon
Di antara runtuhan kapal yang tenggelam di perairan Cirebon, ada beberapa jenis benda yang mungkin tidak termasuk dalam barang komoditi. Beberapa jenis barang tersebut adalah sebuah benda berbentuk tanduk yang dibuat dari logam berlapis emas, sebuah benda berbentuk cumi-cumi (sotong) dari kristal, cetakan tangkup (mould) dari batu sabun (soapstone), serta benda-benda perunggu yang berfungsi sebagai alat-alat upacara agama Buddha/Hindu.
Orang-orang di dalam sebuah kapal merupakan satu komunitas tersendiri, ada nakhoda, kelasi, dan penumpang. Semuanya itu dipimpin oleh seorang nakhoda. Dialah yang memegang kendali di kapal. Demikian juga penumpang kapal yang terdiri dari bermacam status sosial dan profesi. Ada golongan pedagang, mungkin ada bangsawan dan pendeta/bhiksu, dan ada juga penumpang biasa. Semua itu dapat diketahui dari benda-benda yang disandangnya.
Ibn Khordadhbeh, seorang pejabat yang dilantik khalifah Dinasti Abassiyah pada sekitar abad ke-9 Masehi, adalah seorang pedagang yang pernah berkunjung ke Zabag (Śrīwijaya). Dia menulis sebuah buku yang berjudul Kitab al-masalik wa-l-mamalik (Buku tentang Jalan-jalan dan Kerajan-kerajaan). Buku ini berisi tentang semua pos-pos pergantian dan jumlah pajak di setiap tempat yang dikunjunginya. Sebagai seorang pejabat yang dilantik oleh Khalifah tentunya mempunyai tanda legitimasi dan atribut lain yang dibawa dan disandangnya.
Cetakan tangkup yang dibuat dari batusabun (soapstone) berbentuk empat persegi panjang (4,2 x 6,7 cm). Pada salah satu sisinya terdapat kalimat yang ditulis dalam aksara Arab bergaya kufik: “al-malk lillah; al-wahid; al-qahhar” yang berarti “Semua kekuasaan itu milik Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa” dalam dua buah bingkai empat persegi. Kalau diterjemahkan secara harfiah, maka kalimat itu mengandung asma’ul husna, tepatnya merupakan sifat yang dimiliki mausuf (Allah) yang memiliki kekuasan.
Melihat gaya tulisan kufik yang dipakai tampaknya masih kaku jika dibandingkan dengan gaya tulisan kufik pada batu nisan Malik as-Saleh (wafat 1297 Masehi) dari Samudra Pasai (Aceh). Bentuk tulisan ini diduga berasal dari sekitar abad ke-9-10 Masehi yang dikembangkan di daerah Kufah pada masa pemerintahan kekhalifahan Bani Abassiyah (750-870 Masehi).
Sebuah cetakan (mould) dengan ciri-ciri antara lain tulisan digoreskan pada bidang segi empat dalam bentuk negatif. Bidang segi empat yang bertulisan tersebut ada dua buah dibentuk dengan cara “dikorek” sedalam kurang dari 0,5 mm. Dari bagian sisi bawah (dilihat dari bentuk tulisan/aksara) dari bidang segi empat tersebut terdapat garis yang bertemu pada satu titik. Pada titik pertemuan kemudian melebar membentuk corong. Garis berpotongan tersebut mempunyai ukuran lebar 1 mm. dan dalam kurang dari 0,5 mm. Bagian yang membentuk corong berukuran lebar 1-3 mm. Di bagian bawah bidang empat persegi, terdapat dua buah tonjolan yang bergaristengah sekitar 5 mm. dan tinggi sekitar 3 mm. Di bagian atas bidang segiempat terdapat garis yang dibentuk dengan cara dikorek, kemudian permukaan lainnya lebih tinggi dari permukaan atas dua bidang segiempat.
Apabila diperhatikan dengan seksama, benda ini merupakan semacam cetakan untuk logam mulia, seperti emas dan perak. Seharusnya ada sepasang yang saling menangkup, tetapi bagian yang satunya tidak ditemukan. Dua tonjolan bulat yang ada pada permukaan benda tersebut, merupakan semacam pasak pengunci agar tidak bergerak ketika proses pengecoran. Bagian yang berlubangnya seharusnya terdapat pada bagian tangkupan yang hilang. Garis-garis yang bersilang dan bertemu pada satu bentuk corong merupakan tempat mengalirnya cairan logam yang memenuhi bidang segiempat. Tempat memasukan cairan pada bagian yang membentuk corong.
Hasil dari logam yang dicor tersebut berupa lempengan tipis dengan kalimat-kalimat asma’ul husna yang timbul. Kalimat-kalimat tersebut dikelilingi bingkai empat persegi dengan hiasan titik-titik seperti umumnya terdapat pada mata-uang logam. Bagian yang memanjang, dapat dipotong dan dapat pula tidak. Saya belum dapat memastikan fungsi dari benda yang dicetak tersebut. Berdasarkan perbandingan yang diketahui, benda semacam ini berfungsi sebagai jimat dengan tulisan asma’ul husna. Memang dalam keyakinan Islam tidak dikenal jimat, tetapi dalam kenyataannya sebagian umat Islam memandangnya sebagai jimat yang bertulisan asma’ul husna.
Kalau ditelaah dari stempel yang beraksara Arab tersebut, kapal asing yang tenggelam bersama kargonya di perairan Cirebon, diduga kapal yang berasal dari pelabuhan Kufah atau Basra yang sekarang termasuk wilayah Republik Irak. Ini berarti bahwa kapal bersama kargonya berasal dari sekitar abad ke-10 Masehi. Dalam pelayarannya ke arah timur (mungkin ke Kambangputih, Tuban) di perairan Cirebon tertimpa musibah dan tenggelam bersama kargonya. Dilihat dari posisinya di dasar laut, kapal ini tenggelam karena kelebihan muatan. Bagian ruang nakhoda masih tampak utuh (tidak terlalu porak poranda).
Artefak yang berbentuk tanduk pada bagian yang lurus berukuran panjang sekitar 10 cm. Bagian pangkalnya berbentuk segi delapan dengan garis tengah 4 cm. Bagian yang melengkung diberi hiasan berupa ukir-ukiran sulur daun. Bagian pangkalnya berbentuk helaian teratai. Berdasarkan perbandingan dengan benda yang sama dan menjadi koleksi Museum Nasional, benda tersebut merupakan hulu sebuah pedang. Hulu pedang koleksi Museum Nasional tersebut ditemukan di Cirebon dan berasal dari sekitar abad ke-8-9 Masehi.
Ada kemungkinan lain artefak ini berfungsi sebagai hulu pedang (pendek). Cirinya tampak pada sebuah lubang empat persegi panjang pada bagian pangkalnya. Lubang empat persegi panjang ini berfungsi sebagai tempat untuk memasukan bilah senjata tajam pada pegangan. Apabila difungsikan sebagaimana layaknya pedang, pegangan ini terasa tidak nyaman. Mungkin saja senjata tajam dengan gagangnya dari emas berhiasan ukiran ini berfungsi sebagai simbol status dari pemiliknya.
Benda lain yang diduga merupakan hulu pisau atau senjata tajam adalah benda dari kristal yang berbentuk seperti cumi-cumi (sotong). Bagian untuk memasukan bilah senjata berdenah bulat panjang. Pada foto tampak samar-samar lubang yang memanjang dari ujung ke bagian tengah. Bagian atas (lihat foto) ditempatkan melekat pada telapak tangan, sedangkan bagian bawah melekat pada jari-jari tangan.
Hampir seluruh artefak yang diangkut tersebut bukan produk salah satu kerajaan di Nusantara. Ada yang berasal dari Timur Tengah dan India, dan ada pula yang berasal dari Tiongkok. Meskipun demikian, artefak tersebut manfaatnya sangat besar bagi sejarah kebudayaan Indonesia, khususnya sejarah masuknya Islam di Indonesia. Berdasarkan sumber-sumber tertulis para sejarahwan berteori bahwa masuknya Islam di Indonesia dibawa oleh kaum pedagang Islam. Dengan ditemukannya artefak-artefak yang berasal dari negeri-negeri yang beragama Islam dalam konteksnya dengan barang dagangan, teori tersebut semakin mendekati kebenaran. Cetakan beraksara Arab dengan menyebutkan nama-nama Allah, merupakan bukti kuat bahwa Islam masuk melalui “perantara” para pedagang Islam.
2.2 Jejak Persia
Hubungan perdagangan antara Persia dan Nusantara (pada waktu itu dengan Śrīwijaya) berlangsung pada sekitar abad ke-7 Masehi. Pada waktu itu komoditi perdagangan dari Persia berupa barang-barang yang terbuat dari kaca atau gelas yang dikenal dengan sebutan Persian Glass. Benda-benda ini berbentuk vas, karaf, piala, dan mangkuk. Dari Śrīwijaya yang salah satu pelabuhannya adalah Barus (Fansur), para pedagang Persia dan Timur Tengah membawa kapur barus, kemenyan, dan getah damar. Komoditi perdagangan ini sangat digemari di Timur Tengah, Persia, dan India sebagai bahan wangi-wangian.
Persian Glass ditemukan di situs-situs arkeologi yang diduga merupakan bekas pelabuhan kuna. Sebuah penelitian arkeologis di Situs Labo Tua, Barus berhasil menemukan sejumlah besar temuan barang-barang kaca Persia dalam bentuk pecahan dan utuhan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, benda-benda itu mungkin sekarang di tempat asalnya sudah tidak diproduksi lagi. Pelabuhan tempat barang tersebut dikapalkan antara lain dari Siraf yang letaknya di pantai timur teluk Persia.
Masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara melahirkan kerajaan yang bercorak Islam. Salah satu di antaranya adalah Kesultanan Samudera Pasai yang lahir pada sekitar abad ke-13 Masehi dengan sultannya yang pertama adalah Sultan Malik as-Saleh (mangkat 1297 Masehi). Jejak adanya kerajaan ini dapat ditelusuri dari tinggalan budayanya yang berupa batu nisan Sultan Malik as-Saleh. Ada dua hal yang dapat dicermati pada batu nisan ini dan merupakan indikator Persia. Aksara yang dipahatkan pada batu nisan merupakan aksara shulus yang cirinya berbentuk segitiga pada bagian ujung. Gaya aksara jenis ini berkembang di Persia sebagai suatu karyaseni kaligrafi. Kalimat yang dipahatkan bernafaskan sufi, misalnya “Sesungguhnya dunia ini fana, dunia ini tidaklah kekal, sesungguhnya dunia ini ibarat sarang laba-laba”.
Indikator Persia lain ditemukan pada batu nisan Na’ina Husam al-Din berupa kutipan syair yang ditulis penyair kenamaan Persia, Syaikh Muslih al-din Sa’di (1193-1292 Masehi). Ditulis dalam bahasa Persia dengan aksara Arab, merupakan satu-satunya syair bahasa Persia yang ditemukan di Asia Tenggara. Batu nisan ini bentuknya indah dengan hiasan pohon yang distilir (disamarkan) dan hiasan-hiasan kaligrafi yang berisikan kutipan syair Persia dan kutipan al’Quran II: 256 ayat Kursi.
b. Wali Sanga dan Tasawwuf
Wali Sanga di tanah Jawa dikenal sebagai sembilan orang Wali-Ullah yang dianggap sebagai penyiar-penyiar terkemuka agama Islam. Mereka ini sengaja dengan giat menyebarkan dan mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam. Waktu penduduk tanah Jawa masih berkepercayaan lama yang percaya dengan hal-hal gaib, para wali tersebut dipercaya mempunyai kekuatan gaib, mempunyai kekuatan batin yang berlebih, dan mempunyai ilmu yang tinggi. Karena itulah mereka itu dipercaya sebagai pembawa dan penyiar agama Islam ahli dalam tasawwuf.
Wali Sanga jumlahnya ada sembilan orang, yaitu Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Drajat, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Syekh Siti Jenar. Kebanyakan dari gelar-gelar ini diambil dari nama tempat mereka dimakamkan, misalnya Gunung Jati di dekat Cirebon, Drajat dekat Tuban, Muria di lereng Gunung Muria, Kudus di Kudus dsb.
Dalam masa hidupnya mereka menyebarkan agama Islam di daerah tempatnya bermukim. Di wilayahnya itu mereka juga membangun masjid sebagai tempat beribadah. Di daerah sekitar kaki selatan Gunung Muria, banyak ditemukan tinggalan makam para Wali dan masjid tinggalannya, yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Kudus. Masjid yang dibangun adalah Masjid Demak dan Masjid Kudus.
c. Tradisi
Walaupun di Indonesia dikenal mazhab Syafi’i dan menganut Sunnah wal Jamaah, namun di kalangan masyarakat di beberapa tempat di Nusantara masih ditemukan jejak-jejak Syi’ah yang semula dikenal pusatnya di Persia (Iran). Di Timur Tengah dan di Persia, penganut Sunnah wal Jamaah dan penganut Syi’ah tidak sepaham, terutama dalam hal sumber hukum Islam (ijma= kesepakatan para alim ulama). Dalam aliran ini sudah dimulai politisasi agama, terutama pada dasar hukum ijma. Kaum Syi’ah menganggap bahwa yang berhak menjadi Khalifah adalah yang masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya Ijma, dimungkinkan yang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW dapat menjadi Khalifah. Karena itulah yang kaum Syi’ah menganggap al-Qur’an dan Hadist saja yang menjadi dasar hukum agama Islam, sedangkan Ijma dan Qiyash (= perumpamaan) tidak perlu.
Runtuhnya kesultanan Syi’ah tidak menyurutkan ajaran yang “terlanjur” berkembang di masyarakat. Berbagai ritual Syi'ah menjelma menjadi tradisi yang masih ditemukan di beberapa daerah di Nusatara. Di Indonesia penganut Syi’ah jumlahnya tidak banyak (sekitar 1 juta), namun di beberapa tempat tradisi yang biasa dilakukan umat Syi’ah masih dapat ditemukan, dan secara kontinyu dilakukan oleh kelompok masyarakat tersebut.
Dapat dikemukakan sebagai contoh tentang tradisi Syi’ah, misalnya:
Perayaan Tabot, peringatan Hari Arbain atau hari wafatnya Husein bin Ali (cucu Nabi Muhammad) oleh kaum Syiah dalam bentuk perayaan tabot (tabut). Tabot dibuat dari batang pisang yang dihiasi bunga aneka warna, diarak ke pantai, diiringi teriakan “Hayya Husein hayya Husein” yang artinya “Hidup Husein, hidup Husein”. Pada akhir upacara tabot ini kemudian dilarung di laut lepas. Benda yang disebut tabot melambangkan keranda mayat. Perayaan Tabot masih dilakukan masyarakat pada setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu, Pariaman, dan Aceh.
Asyura di Jawa dalam sistem pertanggalan Jawa berubah menjadi bulan Suro, sebutan untuk bulan Muharram (bulan wafatnya Husein). Peringatan Asyura belakangan dikenal dengan istilah “Kasan Kusen”. Di Aceh, Asyura diistilahkan dengan Bulan Asan Usen. Di Makassar Asyura dimaknai sebagai perayaan kemenangan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, sehingga masyarakat merayakannya dengan sukacita. Mereka membuat bubur tujuh warna dari warna dasar merah, putih, dan hitam.
Peringatan Hari Arbain dirayakan juga di Desa Marga Mukti, Pengalengan, Jawa Barat. Ratusan umat Islam Syi’ah memenuhi Masjid al-Amanah untuk melakukan nasyid, doa persembahan kepada Imam Husein, dan ziarah Arbain, doa untuk keluarga Ali bin Abi Thalib.
Debus. Adalah pertunjukan yang hubungannya erat dengan tarekat Rifa’iyah. Tarekat ini didirikan oleh Ahmad al-Rifa’i yang wafat pada tahun 1182 Masehi. Tarekat ini pandangannya lebih fanatik dengan ciri-ciri melakukan penyiksaan diri, mukjizat-mukjizat seperti makan beling, berjalan di atas bara api, menyiramkan air keras (HCl) ke tubuhnya, dan menusuk-nusuk tubuh dengan benda tajam. Penganut Rifa’iyah dengan debus-nya terdapat di Aceh, Kedah, Perak, Banten, Cirebon, dan Maluku bahkan sampai masyarakat Melayu di Tanjung Harapan Afrika Selatan.
d. Kesusasteraan dan Bahasa
Karya-karya sastra bentuk prosa dari Persia sampai pula pengaruhnya kepada kesusasteraan Indonesia, misalnya kitab Menak yang ditulis dalam bahasa dan aksara Jawa yang semula ceritera dari Persia. Dalam bahasa Melayu menjadi Hikayat Amir Hamzah. Kitab Menak pada dasarnya serupa dengan kitab Panji, perbedaannya terletak pada tokoh-tokoh pemerannya. Ceritera-ceritera Menak dalam arti Hikayat Amir Hamzah, biasanya ditampilkan pula dalam pertunjukan wayang golek yang konon diciptakan oleh Sunan Kudus, wayang kulit diciptakan oleh Sunan Kalijaga, dan wayang gedog diciptakan oleh Sunan Giri. Ceritera Menak jumlahnya tidak sedikit, misalnya kitab Rengganis yang banyak digemari oleh masyarakat Sasak di Lombok dan Palembang.
Hasil kesusastraan lain yang mendapat pengaruh Syi’ah adalah:
Kissah Muhammad Hanafiah, mengisahkan pertempuran Hassan dan Husein, anak-anak Khalifah Ali, di medan perang Karbala. Ditulis dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu pada sekitar abad ke-15 Masehi.
Hikayat Amir Hamzah, merupakan kisah roman melegenda berdasarkan tokoh Hamza ibn Abd. Al-Mutalib, paman Nabi Muhammad S.A.W. Kisah roman ini ditulis oleh Hamzah Fansuri, seorang ulama Melayu penganut tasawwuf.
Mir’at al-Mu’minin (Cerminan jiwa insan setia) yang ditulis oleh Shamsuddin as-Sumatrani, seorang penasehat spiritual Sultan Iskandar Muda, murid dan penerus Hamzah Fansuri.
Hamzah Fansuri adalah tokoh terpenting dalam perkembangan Islam dan tasawwuf di Nusantara. Ia adalah orang pertama yang menuliskan seluruh aspek fundamental doktrin sufi ke dalam bahasa Melayu. Ia juga berjasa dalam membawa bahasa dan sastra Melayu ke tingkat baru yang lebih maju.
Bayan Budiman, cerita yang didongengkan oleh seekor burung nuri ini berasal dari ceritera India Śukasaptati, yang isinya memuat pula dongeng-dongeng dari pañcatantra. Di Persia ceritera itu menjadi Tuti-namĕ, dan di Nusantara disadur menjadi Hikayat Bayan Budiman.
Pengaruh Persia dalam hal bahasa juga ada. Beberapa kosa kata, terutama yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan berasal dari kata-kata Persia, misalnya nakhoda, bandar, shahbandar, dan gelar penguasa (raja atau sultan) dengan sebutan Shah atau Syah.
Penutup
Hubungan perdagangan antara kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan Persia (Iran) diduga sudah berlangsung sejak abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Dari hubungan perdagangan ini, kemudian berdampak pada pemikiran keagamaan terutama sufisme atau tasawwuf dengan tarekat-tarekatnya. Selain itu berdampak juga pada unsur-unsur kebudayaan. Beberapa tradisi Syi’ah dan tarekatnya masih tetap dipelihara oleh kelompok masyarakat tertentu di Indonesia. Dalam susastra dan bahasa beberapa karya sastra yang berbau Sufi dan kosa kata Persia diadopsi pada karya sastra Melayu dan kosa kata dalam bahasa Indonesia.
Mungkin masih banyak lagi unsur kebudayaan lainnya yang belum terekam dalam kehidupan bangsa Indonesia yang mendapat pengaruh Persia. Semua ini memerlukan penelitian dari berbagai disiplin ilmu-ilmu humaniora dan sosial, seperti arkeologi dan sejarah, antropologi, sosiologi, agama, linguistik, dan kesusasteraan.
Ada satu hal yang patut kita syukuri dalam kehidupan beragama di Tanah Air Indonesia. Di Tanah Air umat Islam dari berbagai aliran dapat hidup rukun. Keadaan seperti ini sudah “tercipta” sejak masa awal kedatangan Islam di Nusantara. Para penyiar agama melakukan penyampaian dengan cara persuasif dan menyesuaikan dengan budaya setempat, misalnya Wali Sanga menyampaikan syiar Islam dengan cara menggunakan sarana wayang. Tidak ada sedikitpun unsur pemaksaan. Sementara itu di belahan dunia lain, kita lihat bagaimana Libanon, Irak, dan Afghanistan sampai hancur-hancuran sebagai akibat pertikaian sesama umat Islam yang mungkin disebabkan karena adu domba pihak lain.
--------------
*Kerani rendahan pada
Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional
*Kerani rendahan pada
Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional