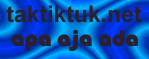Oleh: Nurhadi Rangkuti
Rombongan besar itu berjalan beriringan dengan tertib. Susuhunan Paku Buwana II (1729-1749) mengendarai kuda kesayangannya memimpin perjalanan yang bersejarah. Dua ratus prajurit berkuda dan prajurit lima batalyon berjalan gagah melindungi keluarga raja dan pejabat-pejabat tinggi kerajaan Mataram.
Rabu Paing 17 Muharam 1670 (1745 M), tercatat sebagai perpindahan pusat kerajaan Mataram Islam terakhir dari Kartasura ke Keraton Surakarta. Seluruh harta benda Kerajaan Kartasura diboyong. Sepasang pohon beringin yang masih muda, mahligai, bangsal pengrawit, gajah dan burung kesayangan sri baginda, arca- arca emas untuk upacara, pusaka Kyahi pangarab-arab dan pusaka Kyai Butamancak, kitab-kitab pusaka, dan tak ketinggalan pula pusaka Nyai Setomi.
Bedol negara, mungkin itulah kata yang tepat untuk menggambarkan upacara perpindahan tersebut. Tidak hanya keluarga raja dan pejabat-pejabat tinggi saja yang ikut pindah, tetapi juga tukang emas, tukang besi, penjahit, tukang kayu, tukang batu, abdi dalam keraton, peniup terompet, abdi dalem dapur dengan segala perkakasnya, penangkap-penangkap ikan dengan kail dan perahunya, dan harimau dalam kandangnya.
"Ini jalan yang dilalui mereka dua ratus lima puluh tahun yang lalu", kata Sarosa Suyowiyoto, menunjuk jalan kelas dua beraspal mulus setelah menyeberanginya untuk menuju ke lokasi bekas keraton Kartasura. Jalan itu berada di sebelah utara situs Keraton Kartasura. Menurut pensiunan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo itu, bila menelusuri jalan kuna yang kini telah diaspal itu, lurus ke timur akan sampai di Keraton Surakarta. "Rombongan itu memerlukan waktu empat jam jalan kaki dari Kartasura ke Surakarta, berangkat jam delapan pagi dan tiba pukul dua belas siang".
Jalan kuna itu tidak jauh dari jalan raya Semarang - Surakarta di sebelah utara, yang dulu dibuat Deandels. "Jalan Deandels dibangun setelah Kartasura ditinggalkan", demikian keterangan dari peta kuna.
Dari Plered Ke KartasuraEnam puluh enam tahun sebelum peristiwa perpindahan tersebut, Keraton Kartasura secara resmi pertama kali didiami oleh Sunan Amangkurat II (1677-1702), walau pembangunannya masih belum sempurna. Tepatnya pada tanggal 11 September 1680. Raja Mataram yang semula bernama Pangeran Adipati Anom itu merupakan raja pertama yang menempati Kartasura, keraton dan ibukota baru Kerajaan Mataram pengganti Keraton yang lama di Plered, Yogyakarta.
Pada waktu itu keraton di Plered dalam keadaan yang menyedihkan akibat perebutan kekuasaan yang berlarut-larut antara Sunan Amangkurat I (1646-1647) dan Trunajaya. Sunan Amangkurat I terpaksa meninggalkan keraton Plered setelah istana dikepung dan diduduki Trunajaya. Dalam pelariannya Baginda meninggal dunia di Tegalwangi, kota kecil di sebelah selatan Tegal. Sebelum menutup mata, beliau menyerahkan pusaka-pusaka kerajaan Mataram kepada Pangeran Adipati Anom, yang kemudian menggantikan beliau sebagai Sunan Amangkurat II.
Dengan bantuan Kumpeni, Trunajaya dapat dikalahkan. Tanggal 2 Januari 1680 Raden Trunajaya dihukum mati, ditikam sendiri oleh Sunan Amangkurat II di daerah Malang dekat perbatasan Kediri. Mahkota kerajaan Mataram lalu diserahkan kepada Sunan Amangkurat II. Akan tetapi keadaan keraton Plered sudah tidak terurus dan rusak, menyebabkan Sunan baru itu memutuskan untuk memindahkan ibukota dan keraton ke tempat yang baru.
Pemilihan lokasi keraton dan ibukota Kerajaan Mataram yang baru diserahkan kepada tokoh-tokoh kerajaan. Setelah melakukan survei, mereka berembug dan akhirnya menetapkan tiga lokasi yang dianggap tepat untuk membangun keraton. Lokasi yang diusulkan adalah Wanakerta, Logender danTingkir. Ketiga lokasi ini punya kelaikan tinggal. Logender daerahnya terbuka dan cukup air, Tingkir juga cukup air lagipula daerahnya bagus dan sejuk, sedangkan Wanakerta selain daerahnya datar dan cukup air, juga dekat dengan daerah Pajang dan Mataram.
Setelah panjang lebar membahas ketiga lokasi tersebut, Adipati Hurawan, sesepuh tokoh Mataram, menjatuhkan pilihan pada lokasi di Wanakerta. Terpilihnya Wanakerta karena datarannya luas, air cukup lagi mudah diperoleh dari Pengging, dan memiliki aksesibilitas yang baik dengan tanah Pajang dan Mataram. Adipati Hurawan memberi penjelasan panjang lebar tentang laiknya Wanakerta menjadi lokasi keraton baru. Sri Baginda menyetujui dan berpesan agar pola keraton yang baru mengikuti Keraton Plered.
Tujuh bulan lamanya keraton dibangun dan mendekati selesai. Bentengnya yang luas dan tebal baru dibuat dari gundukan tanah berkeliling dan disangga dengan papan di luar dan di dalamnya, agar tidak runtuh. Semak berduri mengelilingi bagian depan benteng, dan parit berair mengelilingi seluruh kedhaton. Di luar tembok benteng baluwarti bagian selatan terdapat alun-alun.
Loji Kumpeni terletak agak jauh di bagian utara dari alun- alun utara. Semua bangunan hampir belum ada yang berdinding bata, masih berbilik bambu dan beratapkan rumbia. Keraton Kartasura baru kelihatan megah dan sempurna pada tahun 1682.
Pada tanggal 11 September 1680, Sunan Amangkurat II memasuki istana yang baru. Nama Wanekerta diganti menjadi Kartasura Hadiningrat. Dua puluh tiga tahun ia menikmati keraton Kartasura, sambil menghadapi pemberontakan-pemberontakan. Pemberontakan antara lain dilakukan oleh adik Sri baginda sendiri, yaitu Pangeran Puger yang tidak mau mengakui Sunan Amangkurat II menjadi raja, karena ia sendiri telah berhasil merebut kedaton Plered dari tangan pemberontak. Belum lagi pemberontakan dari sisa-sisa pengikut Trunojoyo yang dipimpin oleh Wanakusuma serta didalangi oleh Panembahan Kajoran. Pemberontakan Untung Surapati melawan Kumpeni juga melibatkan keraton Kartasura secara tidak langsung. Kerusakan-kerusakan pun terdapat di lingkungan benteng keraton Kartasura akibat pemberontakan-pemberontakan tersebut.
Sunan Amangkurat II meninggal 1703 dan dimakamkan di Imogiri. Putera mahkota menggantikannya dengan gelar Susuhunan Amangkurat Senopati ing Alaga Sayidin Panata Gama III, atau terkenal dengan nama Sunan Amangkurat Mas (1703-1704). Setelah itu berturut-turut Kartasura dipimpin oleh Sunan Paku Buwana I (1704-1719), Sunan Prabu Hamangkurat Jawi (1719-1727), dan akhirnya Paku Buwana II, yang memindahkan keraton tersebut ke Surakarta.
Sisa-sisa Keraton"Barang-barang berharga keraton Kartasura sekarang berada di keraton Surakarta Hadiningrat, seperti yang tercatat dalam sejarah. Sebagian disimpan di Museum Radyapustaka di Solo", kata Sarosa memberitahu kemana harta kekayaan Kartasura itu berada sekarang setelah diboyong Paku Buwana II pada tahun 1745.
Ketika kaki melangkah memasuki Museum Radyapustaka di Jalan Slamet Riyandi, Solo, pandangan terpaku pada ukir-ukiran kayu yang indah, menghiasi bagian atas pintu dalam museum. "Itu tebeng atau hiasan pintu peninggalan keraton Kartasura", kata Sudaryanto Darmopustoko (60), penjaga museum. Ia lalu menunjukkan benda peninggalan Kartasura lainnya. Lonceng perunggu yang besar, kursi-meja, perlengkapan kuda, wayang dan beberapa alat permainan anak-anak.
Rongsokan mesin jam yang besar teronggok di salah satu ruang museum, sangat menarik perhatian. Rongsokan jam ini pernah diletakkan di alun-alun Keraton Kartasura.
Alex Sudewa, dosen Sanatha Dharma Yogyakarta yang meneliti naskah kuna masa Kartasura, sempat merenungkan keberadaan jam itu di Kartasura pada zamannya. Bagi masyarakat Jawa arloji tidak berbicara apa- apa, hanya sebagai penunjuk waktu. Dipasangnya jam buatan orang Eropa di alun-alun Kartasura, tentunya bukan sekadar iklan dengan wajah sponsor, tetapi jam itu menunjukkan waktu yang bertepatan dengan waktu shalat. Apabila keraton memasang alat penunjuk waktu orang Eropa di tempat umum, menunjukkan adanya perubahan cara berpikir. Apakah benar masa Kartasura adalah zaman kegelapan?, pertanyaan ini mengawali analisanya terhadap naskah-naskah zaman Kartasura, yaitu Serat Menak, Serat Iskandar, Serat Yusuf dan Serat Ngusulbiyat.
Tertarik oleh jam panggung itu, Sarosa bersedia mengantarkan ke tempat dipasangnya jam itu di Situs Kartasura, lokasi bekas keraton yang sekarang berada di Kawedanan Kartasura di Kabupaten Sukoharjo, di Surakarta Jawa Tengah. Sampai di lokasi, Saroso kemudian menunjuk daerah pemukiman padat. "Di situ dulu alun-alun utara. Pagelaran yang terdapat pada alun-alun, sekarang telah pula jadi kampung yang padat". Sulit sekali menelusuri lokasi tepat dipasangnya jam karena padatnya rumah penduduk. Alun-alun bagian selatan pun tidak jauh berbeda.
Menyaksikan bekas Keraton Kartasura (1680-1745) sungguh menyedihkan. Tembok luar keraton atau baluwarti yang terbuat dari bata, telah hancur dan rata dengan tanah, menyisakan sedikit bagiannya di beberapa tempat. Ukuran tembok luar kurang lebih 1 km X 1 km. Tinggi benteng itu lebih dari lima meter, dan tebalnya 2,5 meter. "Dulu prajurit keraton melakukan patroli dengan mengendarai kuda di atas dinding pagar", kata Sarosa meyakinkan.
Di dalam tembok baluwarti, kini dipenuhi dengan perumahan permanen, kebun dan makam. Selain alun-alun, tempat tinggal puteri keraton (keputren) dan petamanan keraton telah menjadi pemukiman padat. Sitihinggil, tempat yang ditinggikan di depan alun-alun, sebagian telah pula menjadi permukiman. Puing-puing bangunan kuna yang tersisa adalah gedung obat (mesiu), bangunan pos jaga Kumpeni. Situs itu kini dipenuhi makam.
Tak ada kolam penuh air di Balekambang keraton, yang letaknya di tenggara keraton. Diganti oleh rumah-rumah dan lapangan sepakbola. Yang tersisa adalah gundukan tanah setinggi lebih dari 20 meter, yang disebut penduduk Gunungkunci. Di puncak "gunung" itu terdapat makam keramat. Tempat ini bekas segoroyoso, tempat rekreasi keluarga keraton, dibangun pada masa Paku Buwana I (1704-1709). Bangunan macam itu mengikuti pola keraton Plered.
Tak ada bangunan keraton yang tampak utuh. Dibandingkan tembok baluwarti, tembok bagian dalam yang mengelilingi keraton atau cepuri, masih kelihatan wujud keseluruhannya. Bagian dalam tembok keraton ini telah dipenuhi makam-makam dari kerabat keraton Surakarta, yang telah bercampur dengan makam-makam penduduk setempat. Di dalam tembok ini juga terdapat mesjid dan beberapa rumah tinggal.
Di antara makam-makam tersebut, teronggok dua buah makam tak terurus berlantai bata. Luasnya sekitar 4 X 6 meter.
"Tempat ini dulu bilik tengah keraton", ujar Saroso Suyowiyoto. Menurutnya, bilik tengah keraton biasanya untuk menyimpan benda-benda pusaka keraton. Makam yang terdapat di situ menurut pensiunan itu adalah makam kosong. "Sengaja dibuat makam, agar lahan ini tidak digunakan untuk kepentingan lain".
Yang kini masih tetap lestari dari bekas ibukota Kartasura itu, adalah nama-nama toponim. Di dalam tembok baluwarti terdapat tempat-tempat yang bernama Keputren, Sitinggil, Alun-alun, Kandangmacan, Sayuran, Bale Kambang, Sanggrahan, Gedung Obat, Pasar, Pelembatok, Sri Penganti, Manggisan, Krapyak, dan Bakalan.
"Manggisan dan Sayuran mungkin dulu kebun manggis dan sayur- sayuran keluarga keraton. Kandangmacan adalah tempat macan sebelum dipertandingkan di alun-alun", kata Sarosa yang telah menulis sejarah lokal keraton Kartasura.
Kartasura memang tinggal puing. "Hancurnya Kartasura karena pemberontakan orang-orang Cina", kata Sarosa. "Lihat kerusakan yang disengaja di tembok cepuri itu. Dulu dijebol oleh berandal- berandal Cina yang sempat menduduki keraton".
"Geger Pacina" Babad Pacina yang ditulis tahun 1775 Saka atau 1853 Masehi oleh Raden Ngabehi Sasradipraja, menceritakan panjang lebar kehancuran keraton Kartasura oleh pemberontakan orang-orang Cina yang menentang Kumpeni Belanda. Peristiwa itu terjadi pada masa pemerintahan Paku Buwana II yang memerintah di Kartasura sejak tahun 1729 sampai kira-kira tahun 1745.
Pemerintahan beliau diwarnai oleh pecahnya perang Cina pada tahun 1740 yang bersumber di Jakarta dan menjalar sampai ke seluruh Pulau Jawa. Pembunuhan massal yang dilancarkan Kumpeni di Betawi terhadap orang-orang Cina, menyebabkan mereka lari ke Jawa Tengah, khususnya di kota-kota pantai utara. Mereka bergabung dengan orang-orang Cina di Jepara, Juwana, Demak, Rembang, Tegal Semarang, dan Surabaya, melawan Kumpeni. Perasaan anti-Kumpeni menjalar pula di ibukota Kartasura. Kekuatan orang-orang Cina ini dimanfaatkan oleh Paku Buwana II untuk membebaskan diri dari Kumpeni dan sekaligus merangkul para pembesar yang anti persahabatan antara raja dan Kumpeni.
Terbunuhnya komandan garnisun Belanda, Van Velzen, di Kartasura pada tanggal 10 Juli 1741, menyebabkan orang-orang Belanda minta bantuan Pangeran Cakraningrat dari Sampang. Pangeran Madura ini memang ingin melepaskan diri dari keraton Mataram dan mendirikan kerajaan baru di bagian timur Pulau Jawa. Sri Sunan cemas dengan perkembangan tersebut, dan akhirnya terpaksa bekerja sama dengan Belanda untuk mencegah kekuasaan Pangeran dari Madura itu. Sikap raja yang tidak tegas itu menyulut pemberontakan. Para pemberontak mengangkat cucu Amangkurat III, sebagai raja yang bergelar Sunan Kuning, dan bersama-sama orang-orang Cina, berhasil menjarah keraton Kartasura. Sri Sunan terpaksa meninggalkan istana yang telah dikepung musuh dan mengungsi selama beberapa lama, sampai akhirnya Kumpeni berhasil membujuk Pangeran Cakraningrat yang menduduki Kartasura setelah menaklukan musuh.
Pada tanggal 21 Desember 1742 Susuhunan Paku Buwana II dapat kembali memasuki Keraton Kartasura dikawal oleh serdadu-serdadu Kumpeni. Akan tetapi keraron telah rusak terbakar setelah diduduki musuh, dan sudah tidak layak sebagai tempat kediaman seorang raja.
Sri Sunan menitahkan kepada dua orang patihnya, Adipati Pringgalaya dan Adipati Sindureja, dan mayor Hogendorf serta bupati lainnya untuk mencari tempat untuk mendirikan keraton baru. Akhirnya desa Sala terpilih dari dua tempat lain yang diusulkan. Desa Sala memang letaknya di tepi sebuah sungai besar, Bengawan Solo, strategis sekali dan mudah didatangi dari pantai bila keadaan memaksa.
Setelah keraton baru itu selesai, Sri Sunan menitahkan untuk pindah dari Kartasura yang telah hancur ke keraton baru di Desa Sala. Keraton baru itu kemudian diberi nama Surakarta Hadiningrat.
Menjadi MakamBangunan istana tempat kediaman raja kini telah berubah menjadi tempat pemakaman kerabat Keraton Surakarta dan penduduk setempat. "Itu makam ibu saya", kata Sarosa menunjukkan lokasi pemakaman umum di dalam tembok cepuri. Makam dari kerabat keraton dipagari tembok dan dibersihkan setiap hari oleh juru kunci.
"Itu adalah makam Kanjeng Raden Ayu Adipati Sedahmirah, pujangga ayu kesayangan Paku Buwana X, yang menulis kitab Ponconiti", kata juru kunci menunjukkan satu-satunya makam yang diberi cungkup dari 27 makam dalam kompleks berpagar tembok. Setiap hari makam keramat itu tak pernah kosong dari peziarah. Banyak peziarah datang meminta maksud dan keinginannya terkabul di tempat itu. Panjang umur, murah rezeki, dapat jodoh, peningkatan karier atau sekadar mencari ketenteraman batin.
Menurut jurukunci, makam-makam penduduk setempat juga banyak yang berasal dari kalangan keraton. Dulu mereka ditugaskan oleh fihak keraton untuk mengurusi keraton Kartasura yang telah ditinggalkan. Menurut kepercayaan Jawa, bila keraton pusat kejayaan dan kebesaran sebuah kerajaan telah dirusak oleh tangan- tangan kotor, tempat itu sudah tidak boleh didirikan pusat pemerintahan lagi. Dan bekas keraton Kartasura pun kini dijadikan makam.