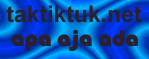Langkahnya begitu pelan, mendaki satu per satu anak tangga di Gedung Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Pustlit Arkenas), Jalan Raya Condet Pejaten, Nomor 4, Jakarta Selatan, Rabu (23/6/2010). Tangan kanannya memegang pagar tangga, sedangkan tangan kirinya menggenggam tongkat. Sejenak dia berhenti, tetapi terus melangkah lagi menuju kantornya di lantai dua, tepat di depan tangga. Hanya langkah lambat itu yang menandai usia menggerogoti fisik RP Soejono.
RP Soejono adalah salah satu arkeolog Indonesia pertama. Bahkan, pria kelahiran Mojokerto, 27 November 1926, itu adalah pakar prasejarah pertama negeri ini. Meski usianya sepuh, dia tidak memiliki penyakit degeneratif. Justru pada hari tuanya dia tetap sibuk, seperti menulis artikel dan memeriksa disertasi mahasiswa dari dalam dan luar negeri.
Ada kejadian lucu soal memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang tengah menyusun disertasi. Mahasiswa itu berasal dari Malaysia. Untuk membimbing calon doktor seperti itu, Soejono sebagai pembimbing mendapat honor Rp 400.000 per mahasiswa. Nah, pembayaran dari Malaysia ternyata melalui bank yang tidak ada cabangnya di Indonesia. Alhasil, kiriman itu pun tidak sampai ke tangan Soejono.
"Saya tidak tahu kiriman uang itu sampai di mana. Saya juga tidak menagih. Entah kapan persisnya, saya sudah lupa," kata Soejono di ruang kerjanya yang penuh berisi buku dan disertasi para mahasiswa.
Sebagai profesor prasejarah, Soejono membimbing banyak calon doktor dari berbagai negara. Dulu, dia membimbing mahasiswa, antara lain dari Perancis, Belanda, Australia, Amerika Serikat, India, Jepang, Malaysia, dan Indonesia. Semasa aktif, Soejono mengajar di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Udayana, Universitas Hasanuddin, dan beberapa universitas lainnya. Sekarang, dia hanya membimbing satu kandidat doktor dari Malaysia.
"Ada dua lagi dari Malaysia, tetapi saya tolak," ujar Soejono. Dia menolak karena usianya terus meninggi dan fisiknya tidak sekuat dulu lagi. Padahal, sampai masa pensiun usia 65 tahun di Puslit Arkenas, Soejono masih aktif mengunjungi situs, termasuk mendatangi situs-situs yang berada di perbukitan atau pegunungan.
Bagi mahasiswa ingin melanjutkan studi mengenai Indonesia sebaiknya mengambil kuliah di dalam negeri, bukan di luar negeri.
Perjalanan hidupPerjalanan hidup mantan Kepala Puslit Arkenas itu penuh warna. Dia berpindah kota mengikuti ayahnya, Soeroso, dulu anggota Volksraad pada zaman Belanda dan Residen Kedu. Sekolahnya pun berantakan karena zaman bergolak. Namun, dia lancar berbahasa Belanda.
Ketika Soejono berusia 19 tahun, di daerah Malang, Jawa Timur, dia ditangkap Belanda. Dia dijebloskan ke dalam bui sebesar lemari pakaian berukuran sempit dan gelap. Namun, tentara Belanda yang menangkapnya bingung karena Soejono pandai berbahasa Belanda. Tentara tersebut akhirnya membebaskan dia.
"Tentara Belanda itu menganggap saya mungkin orang penting sehingga tidak berani membunuh saya. Saya pun selamat. That was the best year of our life," kata Soejono mengenang.
Sebagai arkeolog senior, Soejono mengalami masa awal tumbuhnya arkeologi di Indonesia. Dari bangsa Belanda, bangsa Indonesia mengenal arkeologi dan memiliki arkeolog. Dia memilih spesialisasi prasejarah karena ketika itu tidak ada yang mengambil spesialisasi tersebut. R Soekmono dan Satyawati Suleiman mengambil spesialisasi klasik, sedangkan Boechari mendalami studi epigrafi. Alhasil, hanya dia yang menjadi murid HR van Heekeren.
"Enaknya, karena belum banyak teori tentang prasejarah Indonesia, saya tinggal bikin teori sendiri," kata suami Hangarini Ambaroekmi Vascayati itu sembari terkekeh.
Dari situ, Soejono menilai bagi mahasiswa ingin melanjutkan studi mengenai Indonesia sebaiknya mengambil kuliah di dalam negeri, bukan di luar negeri. Alasannya, rakyat Indonesia lebih tahu perihal bangsanya sendiri. Biarkan saja bangsa asing yang sibuk berdatangan ke Indonesia untuk mempelajari betapa kayanya negeri ini.
"Akarnya ada di sini. Mengapa tidak mempelajari dari akarnya langsung di sini," katanya singkat. Dia mencontohkan, disertasinya pada Juni 1977 tentang "Sistem- Sistem Penguburan pada Akhir Masa Prasejarah di Bali mengenai situs Gilimanuk" masih dapat diperbaiki oleh peneliti selanjutnya. Bukan berarti semua obyek yang sudah menjadi skripsi, tesis, dan disertasi tidak dapat digugat lagi. Justru penelitian tentang obyek tersebut harus terus dikembangkan.
"Situs Gilimanuk sangat luas dan perlu penelitian lebih lanjut. Apalagi situs lain di Indonesia," imbuh penerima gelar doctor honoris causa dari Universite d’Aix Marseille II itu.
Lagi pula, meski sekarang banyak arkeolog muda dan ilmu arkeologi tidak lagi hanya dipelajari segelintir orang, tetap saja banyak kepurbakalaan di Nusantara yang perlu penelitian lebih lanjut. Kepurbakalaan di Indonesia timur, misalnya. Belum lagi menguak secara lebih menyeluruh dari aneka obyek arkeologi yang pernah diteliti.
"Negeri ini membutuhkan banyak arkeolog," katanya.
Dia tidak ingin arkeologi Indonesia lebih dipahami bangsa asing. Apalagi jika bangsa lain menguasai kepurbakalaan Indonesia. Dia tidak memungkiri ada banyak tesis dan disertasi karya orang asing yang mengambil obyek Indonesia. Namun, akan lebih menggembirakan jika orang Indonesia sendiri yang menguasai, memahami, mengembangkan, dan memperkenalkannya kepada dunia internasional. Terutama karena Indonesia begitu heterogen dalam berbagai hal. Setiap daerah memiliki suku bangsa, bahasa, makanan, bentuk rumah, tradisi, dan pakaian khas yang berlainan.
Tidak banyak bangsa yang memiliki sejarah begitu kaya dan lengkap. Indonesia sangat beruntung karena memilikinya. Lihat saja, Indonesia memiliki manusia purba. Kepurbakalaan klasik Hindu-Buddha begitu banyak. Borobudur hanya satu-satunya di dunia ini. Coba cari, apa ada yang mirip dengannya? Bayangkan jika Indonesia tidak memiliki kekayaan tersebut. Mungkin akan mengaku-aku kekayaan bangsa lain," urainya penuh semangat.
Sumbangan arkeologi bagi Indonesia ini adalah memberikan kebanggaan bahwa bangsa ini begitu besar. Tugas arkeolog adalah terus menguak betapa rakyat Indonesia senantiasa terlibat dalam perkembangan sejarah bangsa dan negaranya. Bahkan, sejarah bangsa ini selalu terkait dengan perjalanan sejarah dunia.
"Dalam setiap periode sejarah, rakyat dan pemimpin bangsa bersatu. Namun, kini pemimpin jauh dari bangsanya sendiri. Mereka hidup dalam dunia lain. Mengabaikan rakyatnya. Menyedihkan. Kalau tahu akan begini, mungkin para pejuang kemerdekaan akan sedih. Untuk apa mereka meraih kemerdekaan? Kemerdekaan adalah jembatan emas menuju kemakmuran. Sayangnya, para pemimpin lebih senang menggerogoti emas jembatan tersebut sehingga jembatannya runtuh dan kemakmuran semakin jauh," katanya. (Ida Setyorini)
(Kompas, Senin, 28 Juni 2010)