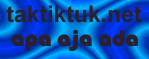AGUS ARIS MUNANDAR
DEPARTEMEN ARKEOLOGI
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA (FIB UI)
I
“…Janganlah mabuk kebudayaan kuno,tetapi jangan mabuk kebaratan juga;ketahuilah dua-duanya, pilihlah mana yang baikdari keduanya itu, supaya kita bisa memakainyadengan selamat di dalam hari yang akan datang kelak”(Poerbatjaraka 1986: 32)Pernyataan tersebut dikemukakan oleh R.M.Ng.Poerbatjaraka ketika tengah berlangsungnya polemik kebudayaan di antara para cendekiawaan dalam tahun 1935—1936. Polemik tersebut mengemuka karena adanya kesadaran perihal bentuk kebudayaan seperti apa yang akan mengisi Indonesia ketika merdeka kelak. Di antara dua pihak yang saling berpolemik, yaitu Sutan Takdir Alisjahbana dan Sanusi Pane, pendapat Poerbatjaraka yang berjudul “Sambungan Zaman” seakan-akan mengingatkan mereka dan seluruh bangsa yang bersiap untuk merdeka pada masa itu bahwa negeri ini telah mempunyai sejarah panjang. Bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari ini sebenarnya adalah kelanjutan dari masa sebelumnya, begitu pula halnya dalam bidang kebudayaan. Untuk memajukan kehidupan bangsa memang perlu masukan dari kebudayaan yang lebih maju, dalam hal ini kebudayaan barat, tetapi tetap harus memperhatikan pencapaian kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia sendiri.
Perhatian terhadap arkeologi dalam bentuk kajian tersendiri di wilayah Indonesia awalnya telah disemaikan oleh Sir Th.S.Raffles. Walaupun Raffles hanya singkat saja menduduki jabatan penguasa tertinggi penjajahan Inggris di Nusantara, namun minatnya terhadap sejarah dan peninggalan kuna di Jawa, telah mendorongnya untuk menerbitkan karya yang monumental berjudul The History of Java (1817). Setelah buku Raffles tersebut dipublikasikan, makin banyak saja bangsa Eropa, terutama orang Belanda yang berminat untuk meneliti peninggalan kuna di Indonesia. Pada tahun 1875 didirikan perkumpulan peminat kajian arkeologi di kalangan orang Belanda (Archaeologische Vereeniging). Kegiatan perkumpulan ini antara lain berhasil menemukan tengkorak Pithecanthropus Erectus, pada tahun 1891 oleh E.Dubois. Penelitian arkeologi kemudian menjadi agenda resmi kegiatan pemerintah kolonial Hindia-Belanda, karena pada tahun 1901 dibentuklah Commissie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundig onderzoek op Java en Madura. Kegiatan komisi ini berkembang dengan pesat, maka pada tahun 1913 dibentuklah lembaga yang mengurusi kegiatan penelitian purbakala (arkeologi) dinamakan Oudheidkundige Dienst (Dinas Purbakala) (Sedyawati & Pieter Ter Keurs 2005: 8). Di bawah naungan lembaga tersebutlah penelitian arkeologi dan sejarah kuna Indonesia yang dilakukan oleh Poerbatjaraka mulai dilaksanakan.
Pada tahun 1914 terbitlah beberapa karangan Poerbatjaraka yang berkenaan dengan sejarah kuna masa Majapahit yang juga menyinggung perihal peninggalan-peninggalan kuna kerajaan tersebut. Karangan itu antara lain berjudul ”De dood van R.Wijaya den eersten koning en stichter van Majapahit”, dalam T.B.G. (Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde) LVI (afl.1-2), halaman 143—148. Pada tahun 1917 terdapat juga tulisan tentang arca di Candi Jawi, berjudul ”Het beeld van Tjandi Djawi”, dalam Oudheidkundige Verslag 1e kwart, halaman 143-151, dan satu karya penting lainnya berkenaan dengan sejarah Sunda Kuna terbit dalam tahun 1919 berjudul ”De Batoe-toelis bij Buitenzorg”, TBG LIX (afl.4) halaman 380-418. Karya tulis tentang Sunda Kuna tersebut yang sampai sekarang terus diacu dan diperbincangkan oleh para ahli manakala mereka meneliti perkara yang sama, karya Poerbatjaraka tersebut sangat monumental karena mengungkap salah satu permasalahan dalam prasasti, yaitu kronologinya.
Cukup banyak karya tulis Poerbatjaraka yang menelisik tentang berbagai hal kemasalaluan. Pada umumnya tentang bahasa, karya sastra Jawa Kuna, sejarah kuna, kajian prasasti (epigrafi), dan sedikit tentang arkeologi. Dapat dipahami apabila telaah Poerbatjaraka perihal arkeologi Indonesia cukup terbatas, karena memang dasar perhatiannya berawal dari penelisikan terhadap bahasa dan sastra, terutama dari masa Jawa Kuna. Berhubung terdapat pertalian yang erat antara bahasa dan Sastra Jawa Kuna dengan arkeologi Hindu-Buddha di Jawa, maka telaah yang dilakukan Poerbatjaraka tentang bidang yang digelutinya niscaya akan tetap berpengaruh terhadap perkembangan ilmu arkeologi Indonesia, terutama arkeologi Hindu-Buddha.
II
”Pintu masuk” perhatian Poerbatjaraka terhadap arkeologi adalah studi epigrafi (Penelisikan terhadap aksara, isi, dan kaitan sejarah suatu prasasti). Walaupun penelisikan di bidang epigrafi tersebut tidak terlalu banyak, namun hampir semua prasasti yang dikajikan penting bagi pengembangan epigrafi Indonesia kuna. Dapat kiranya Poerbatjaraka disebut sebagai ahli epigrafi perintis dari kalangan bangsa Indonesia, karena semula bidang tersebut selalu ditangani oleh orang-orang Belanda (Boechari 1964: 119).
Dalam kajian epigrafi karya Poerbatjaraka sangat banyak dan berkenaan dengan beberapa prasasti yang dianggap penting serta masih menyimpan sejumlah permasalahan. Prasasti-prasasti yang dibahas antara lain adalah pembacaan ulang terhadap prasasti Batu Tulis di Bogor. Prasasti ini telah dikaji oleh para ahli peminat Sunda Kuna, misalnya Frederich, K.F.Holle, C.M.Pleyte, dan Hoesein Djajadiningrat. Poerbatjaraka berhasil melakukan pembacaan secara lebih baik, serta sumbangan kajiannya yang penting adalah berhasil menafsirkan secara tepat kronologi prasasti itu yang menurutnya candrasangkala itu seharusnya berbunyi ”panca pandawa nge(m)ban bumi” dengan nilai angka 1255 S (1355 M) (Sutaarga 1965: 25--6). Prasasti lainnya yang dibahas oleh Poerbatjaraka adalah yang dipahatkan pada asana arca Aksobhya di Simpang Surabaya. Walaupun prasasti tersebut sudah dibahas oleh H.Kern, Poerbatjaraka berhasil membacanya kembali dengan sempurna, tafsiran yang dikemukakannya bahwa prasasti ini disusun oleh Nada, ayah Mpu Prapanca, walaupun prasasti ini bertarikh 1211 S, namun baru ditulis sesudah tahun 1272 S, demikian menurut Poerbatjaraka (Boechari 1964: 119—20).
Kajian epigrafi lainnya yang dilakukan oleh Poerbatjaraka adalah terhadap prasasti Balawi (tahun 1227 S) dan Sukamerta (tahun 1218 S). Berdasarkan penelitiannya terhadap isi kedua prasasti tersebut dapat diketahui bahwa keempat istri raja Krtarajasa Jayawarddhana (Raden Wijaya) adalah putri-putri raja Krtanagara. Jayanagara adalah putra Krtarajasa dari permaisurinya yang merupakan putri tertua raja Krtanagara. Hal yang sama juga disebutkan dalam uraian prasasti Sukamerta bahwa ibu Jayanagara adalah putri tertua Krtanagara yang menjadi permaisuri Krtarajasa.
Tafsiran semula menyatakan bahwa Jayanagara adalah putra Krtarajasa dari Dara Petak, putri Malayu yang dibawa ke Jawa sebagaimana yang dinyatakan dalam Pararaton. Pemberontakan-pemberontakan Ranggalawe dan Lembu Sora semula dianggap terjadi dalam masa pemerintahan Jayanagara, bahwa rakyat Majapahit tidak menyukai raja Jayanagara karena ia keturunan dari luar Jawa. Hasil penelitian Poerbatjaraka secara jelas menyatakan bahwa Jayanagara bukan keturunan luar Jawa, melainkan cucu Krtanagara, raja terakhir Singhasari. Lagi pula pemberontakan Ranggalawe dan Lembu Sora dalam Pararaton justru terjadi masih dalam era Krtarajasa, bukan dalam masa Jayanagara. Hasil kajian Poerbatjaraka tersebut sangat membantu semangat persatuan Nusantara, bahwa pada masa Majapahit tidak ada rasa suka atau tidak suka antarsuku-suku bangsa yang hidup di Jawa atau luar Jawa (Wibowo 1976: 79). Apabila hasil penelisikan sarjana-sarjana Belanda terdahulu itu tidak diluruskan oleh Poerbatjaraka, sangat mungkin rasa sentimen antarsuku masih tetap saja mengendap hingga sekarang.
Poerbatjaraka juga memberikan pembacaan yang tepat dari bait ke-14 prasasti Pucangan bagian yang berbahasa Sansekerta. Melakukan pembacaan yang lebih memuaskan pada uraian yang berbahasa Jawa Kuna hingga bait ke-17, namun selebihnya belum dilakukannya sehubungan cetakan kertas (abklats) prasasti tersebut tidak terlalu baik (Boechari 1964: 121). Prasasti batu Plumpungan juga dibahas oleh Poerbatjaraka, ia membantah pendapat J.G.de Casparis yang menyatakan bahwa prasasti itu bersifat agama Buddha. Menurut Poerbatjaraka prasasti itu bersifat Hindu-Saiva, karena nama Isa yang disebut-sebut dalam prasasti adalah nama lain dari Siva, sementara De Casparis menyatakan bahwa Isa adalah sebutan bagi Buddha. Satu nama tempat dalam prasasti Plumpungan dibaca oleh De Casparis dengan Trigramvya, namun pembacaan itu dibetulkan oleh Poerbatjaraka menjadi Trigostya, yang dalam bentuk biasa diucapkan Trigosti yang merupakan sinonim dari Trisala, kata ini sampai sekarang masih tersisa menjadi Salatiga (Boechari 1964: 122). Perhatian Poerbatjaraka pada bidang epigrafi tersebut lalu dituangkannya dalam bentuk buku sejarah Indonesia yang berjudul Riwayat Indonesia I (terbit tahun 1951). Dalam bukunya Poerbatjaraka membuktikan bahwa untuk melakukan historiografi sejarah kuna Indonesia harus berbeda dengan cara menyusun sejarah Indonesia modern. Cara penulisan sejarah yang telah dilakukan oleh Poerbatjaraka menyajikan hal-hal yang sudah pasti, lalu menyampaikan perkara yang masih harus dibuktikan lebih lanjut, dan sejumlah masalah yang masih perlu mendapatkan pemecahannya sesuai dengan temuan data di masa kemudian (Wibowo 1976: 80). Hanya saja Poerbatjaraka tidak sempat lagi menerbitkan buku Riwayat Indonesia Jilid II, namun apa yang telah dilakukan dalam bidang epigrafi dan penyusunan sejarah Indonesia kuna tetap dapat dijadikan dasar bagi kajian lanjutan di masa mendatang.
III
Memang kajian khusus yang dilakukan oleh Poerbatjaraka berkenaan dengan arkeologi sangat terbatas. Penelisikan yang dilakukannya atas berbagai permasalahan masa Hindu-Buddha lebih bertumpukan kepada sumber tertulis, baik yang berupa prasasti atau pun karya sastra. Walaupun demikian tinjauan dan pembicaraan terhadap data arkeologis atau pengajuan permasalahan arkeologis yang harus dipecahkan kerapkali muncul dalam berbagai karangannya. Karya yang sebenarnya sarat dengan permasalahan arkeologis adalah disertasi Poerbatjaraka yang berjudul Agastya in den Archipel (1926), yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul Agastya di Nusantara (1992). Kajian yang dilakukannya dapat disebut sebagai perpaduan dari berbagai disiplin keilmuan seperti filologi, epigrafi, arkeologi, sejarah, dan folklore Jawa. Permasalahan yang dikemukakan dalam karya tersebut sebenarnya bersifat tunggal, yaitu mengemukakan kehadiran tokoh rsi yang diperdewa sebagai penyebar agama Hindu-Saiva di wilayah kepulauan Indonesia dalam zaman Hindu-Buddha.
Dalam upaya mendudukkan pokok persoalan utamanya, yaitu tokoh Agastya, Poerbatjaraka harus mengeksplorasi dan menjelajah berbagai sumber baik yang berupa prasasti dan karya sastra Jawa kuna, India, Nepal, cerita wayang, dan juga hasil penelitian para sarjana terdahulu. Kajian yang cukup penting adalah kesimpulannya tentang arca Agastya yang semula dipercaya oleh para ahli Belanda antara lain N.J.Krom sebagai arca Siva Mahaguru. Anggapan terdahulu yang telah dipercaya secara luas bahwa arca orang tua yang berperut buncit, berjanggut, bertangan dua dan seringkali disemayamkan di relung selatan candi Hindu-Saiva di Jawa, dianggap sebagai tokoh arca Mahaguru. Setelah melalui argumentasi yang panjang lebar tentang Bhattra Guru yang dikenal di Jawa baik menurut uraian sumber tertulis ataupun penggambaran wayang kulitnya, Poerbatjaraka menyatakan bahwa arca orang tua berjanggut dan berperut buncit itu bukanlah Mahaguru, melainkan arca Agastya (Poerbatjaraka 1992: 106—37). Dikemukakan oleh Poerbatjaraka bahwa Agastya ialah tokoh pendeta murid kesayangan Siva, ia menyebarkan agama Hindu-Saiva di Nusantara melalui jalur perjalananan laut. Antara abad ke-7—9 kedudukan Agastya dalam ritus pemujaan Hinduisme mencapai puncaknya, bahkan ia diseru dan disejajarkan bersama-sama Siva dan Durga (Poerbatjaraka 1992: 16—17, 72, 78).
Telaah dengan argumen yang panjang lebar dan begitu rinci juga dilakukan Poerbatjaraka ketika ia mencoba menjelaskan bahwa istilah Vaprakesvara dalam prasasti Kutai kuna, atau Baprakeswara demikian penyebutannya dalama beberapa prasasti Jawa Kuna. Hasil penelitian Poerbatjaraka menyimpulkan bahwa Vaprakesvara/Baprakeswara adalah nama tokoh bukannya nama tempat. Tokoh yang dimaksudkan tidak lain ialah Agastya, jadi Baprakeswara adalah nama lain dari Agastya.
Waprakeswara menurut H.Kern adalah ”api suci” tempat membakar berbagai sajian bagi para dewa (Kern 1917: 15). Pendapat itu tidak disetujui oleh J.Ph.Vogel, Vogel berpendapat bahwa Waprakeswara adalah adalah nama tempat atau bangunan suci untuk memuja Siva yang diseru juga dengan Isvara (Vogel 1918: 203—5). Krom mempersamakan istilah Waprakeswara dengan Baprakeswara yang tercantum dalam uraian beberapa prasasti Jawa Kuna. Di India tidak pernah ditemukan istilah Waprakeswara/Baprakeswara, karenanya ia mengajukan pendapat bahwa Vaprakesvara/Baprakeswara adalah tempat suci yang berpagar sebagaimana layaknya punden-punden desa yang masih dijumpai di beberapa tempat di Jawa. Kata vapra atau vapraka sebenarnya berarti pagar atau pagar keliling (Krom 1933: 176—7). Akan halnya W.F.Stutterheim menyetujui pendapat Krom, ia menambahkan bahwa tempat/bangunan suci berpagar tersebut merupakan candi sebagai makam raja. Roh raja yang telah meninggal dan dianggap menjadi bhatara atau dewata dianggap bersemayam di tempat tersebut (Stutterheim 1934: 203—4).
Semua pendapat para ahli terdahulu tidak disetujui oleh Poerbatjaraka, Waprakeswara/Baprakeswara berasal dari kata bapra-bhattaraka atau bappa-bhattaraka suatu seruan untuk seorang tokoh penting dalam sistem religi Hindu-Saiva. Poerbatjaraka menyatakan tokoh tersebut tidak lain dari Agastya yang merupakan salah seorang pendeta penting dalam aliran Hindu-Saiva. Kata punyatama ksetre yang mendahului kata Waprakeswara dalam prasasti Kutai Kuna selain menunjukan lokasi, dapat juga ditafsirkan sebagai ”lapangan suci” atau guru atau sesembahan (”pupunden”) (Poerbatjaraka 1992: 88). Dalam hal ini Poerbatjaraka bermaksud menyatakan bahwa Agastya bagaikan ”lapangan suci” karena keluasan ilmunya dan merupakan guru karena kedalaman pengetahuannya mengenai Isvara (Siva).
Menurut Poerbatjaraka selanjutnya bahwa pada awal perkembangan agama Hindu di Nusantara (dalam prasasti-prasasti Kutai Kuna) nama yang dikenal untuk menyeru Agastya adalah Baprakeswara, prasasti-prasasti yang lebih kemudian menyebut Hyang Baprakeswara di samping atau bersama Agasti, tahap selanjutnya dalam prasasti yang lebih muda disebut dengan Baprakeswara sri Haricandana Agasti, dan pada tahap paling akhir yang disebut dalam prasasti hanyalah Haricandana Agasti (prasasti-prasasti Bali).
TAHAPAN PENYEBUTAN AGASTYA MENURUT POERBATJARAKA VAPRAKESVARA --> HYANG BAPRAKESVARA AGASTI --> BAPRAKESVARA SRI HARICANDANA AGASTI --> HARICANDANA AGASTI
Hal yang menarik selanjutnya adalah pernyataan Poerbatjaraka dalam bukunya Riwayat Indonesia I (1951), ia menyatakan sebagai berikut:
- ”Di dalam batu tulis jang terbelakang itu ada nama tempat jang sangat penting buat pengetahuan kita tentang agama jang dipeluk oleh Sang Mulawarmman, jakni Waprakeswara nama suatu tempat sutji; dan di dalam tempat itu pulalah selamatan (kenduri) Sang Mulawarmman itu dilakukan.
Nama Waprakeswara ini nanti di tanah Djawa timbul kembali dalam bentuk Baprakeswara. Telah njata sekali, bahwa di Tanah Djawa, jang dinamakan Baprakeswara itu ialah suatu tempat sutji yang disebut selalu berhubungan dengan dewa besar tiga, jakni Brahma-Wisnu-Siwa. Dengan kata lain dewa besar tiga tersebut, di Tanah Djawa ialah dimuliakan di tempat sutji, jang bernama Baprakeswara, atau tempat suci Baprakeswara itu ialah tempat candi Brahma-Wisnu-Siwa” (1951: 11).
Dalam hal ini pendapat Poerbatjaraka agak sedikit berbeda dengan yang diutarakannya pada tahun 1926 dalam uraian disertasinya. Semula ia menyatakan bahwa Waprakeswara adalah nama lain dari Agastya, namun dalam buku tahun 1951 dinyatakannya bahwa bahwa Waprakeswara/Baprakeswara adalah suatu tempat suci. Di tanah Jawa Baprakeswara itu dapat berupa lahan suci tempat berdirinya candi-candi yang dipersembahkan kepada Brahma-Wisnu-Siwa. Dalam pada itu pendapat terbaru yang berkenaan dengan Waprakeswara dikemukakan oleh Hariani Santiko. Intinya menyetujui pendapat Poerbatjaraka yang memandang Waprakeswara sebagai tempat atau lokasi yang suci, hanya saja dalam argumennya ia mengacu kepada sistem ritus yang diadakan oleh para pendeta dalam zaman perkembangan ”agama Weda”. Menurut Hariani Santiko kata wapra atau wapraka dalam bahasa Sansekerta tidak hanya berarti pagar juga dapat diartikan sebagai gundukan atau tumpukan, kata tersebut setara dengan barhis yang artinya gundukan atau bantalan (rumput) untuk duduk iswara atau dewa (Santiko 1989: 4). Pernyataan selanjutnya sebagai berikut:
”...Waprakeswara dalam prasasti Kutei tidak lain adalah lapangan suci untuk melaksanakan upacara bersaji sesuai dengan ketentuan Weda-Samhita dan kitab-kitab Brahmana, wapra atau wapraka disini yang dimaksud adalah barhis yang disusun berlapis-lapis di sekitar tungku suci (agni) di dalam vedi.Setelah agama Hindu mulai menyebar di Jawa, peranan para pendeta Weda itu ”diambil alih” oleh seorang pendeta besar murid dewa Siwa yaitu Agastya. Oleh karenanya tempat suci untuk tokoh ini tetap dikenal sebagai w(b)aprakeswara (Santiko 1989: 6).
Demikinlah perihal Waprakeswara yang agaknya merupakan tempat atau lahan suci untuk memuja para dewa, pendapat Poerbatjaraka tentang hal itu telah lama dikemukakan sebelumnya, begitupun mengenai hubungan antara Waprakeswara dengan Agastya telah lama dikemukakan oleh Poerbatjaraka secara meyakinkan, jadi sebenarnya dalam kajian Hariani Santiko tidak terdapat kesimpulan yang baru.
Ungkapan secara tidak langsung tentang kajian arkeologi lainnya dikemukakan oleh Poerbatjaraka manakala membahas keraton kerajaan Sunda-Pajajaran. Sebagaimana diketahui dalam beberapa sumber tertulis Sunda Kuna, antara lain Carita Parahyangan, disebutkan adanya bangunan keraton kerajaan Sunda yang disebut Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Menurut Poerbatjaraka kata Pakuan-Pajajaran yang sering disebut-sebut dalam berbagai sumber sejarah Sunda kuna, bukan dari kata pohon paku (pakis) yang berdiri sejajar di pusat kerajaan itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh K.F. Holle (1869), atau berarti titik pusat alam (poros dunia) seperti yang dikemukakan oleh G.P.Rouffaer (1919). Tafsiran Poerbatjaraka tentang Pakuan Pajajaran adalah ”de aan rijen staande hoven” (bangunan istana yang berjajar). Menurutnya kata Pakuan sangat mungkin berasal dari kata pa + kuwu + an pakuwan atau pakuwon, kata ini masih bertahan dalam bahasa Jawa pantura sekarang, berasal dari kata akuwu atau kuwu yang berarti pemimpin daerah tertentu (Poerbatjaraka 1921: 401). Dengan demikian nama keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati seharusnya berwujud 5 bangunan keraton yang berdiri berjajar.
Pendapat Poerpatjaraka tersebut meninggalkan masalah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bidang arkeologi. Mengenai pendapat Poerbatjaraka itu, Ayatrohaedi melanjutkan:
”Barangkali keraton induk terletak di tengah jajaran itu, walaupun memang terbuka kemungkinan bahwa bangunan induk itu terletak paling ujung (depan ataupun belakang), jika kita mengingat bahwa namanya selalu disebutkan sebagai unsur terakhir dari kompleks bangunan keraton itu” (Ayatrohaedi 1978: 52).
Agaknya tafsiran Ayatrohaedi yang menyatakan bahwa bangunan Suradipati tersebut merupakan bangunan induknya, dapat diterima, mengingat bangunan-bangunan keraton lama lainnya juga mempunyai unsur kata sura, misalnya Surawisesa adalah keraton kerajaan Sunda di Kawali, Surasowan nama bagi keraton kesultanan Banten, dan Surakarta adalah nama tempat tinggal penguasa Jayakarta sebelum dikuasai VOC Belanda. Kemudian dipertanyakan juga oleh Ayatrohaedi mengenai arah hadap bangunan-bangunan keraton yang berjajar itu. Menurutnya berdasarkan uraian cerita-cerita pantun Sunda, besar kemungkinan jika jajaran itu membujur dari utara-selatan, bukannya melintang dari barat ke timur (1978: 52). Penafsiran tersebut agaknya didasarkan pada kisah-kisah pantun, data peninggalan arkeologi, interpretasi atas laporan perjalanan orang-orang Belanda dan juga berdasarkan perbandingan struktur bagian-bagian keraton dari masa perkembangan Islam di Nusantara.
Berawal dari pendapat Poerbatjaraka tentang adanya 5 bangunan keraton yang berjajar, maka kajian arkeologi mendapat peluang untuk menafsirkan lebih jauh lagi perihal keraton tersebut. Saleh Danasasmita dalam laporan penelitiannya tahun 1979 yang berjudul ”Lokasi Gerbang Pakuan dan Rekonstruksi Batas-batas kota Pakuan Berdasarkan Laporan Perjalanan Abraham van Riebeeck dan Ekspedisi VOC lainnya (1687—1709)” menyatakan bahwa kompleks keraton Pakuan-Pajajaran terletak di kota Bogor sekarang, di utara kompleks keraton terdapat tanah lapang luas (alun-alun) dan sangat mungkin bangunan-bangunan keraton tersebut berderet menghadap ke utara. Laporan Danasasmita itu kemudian dicetak dalam buku Mencari Gerbang Pakuan dan Kajian lainnya Mengenai Budaya Sunda (2006), dalam buku itu dinyatakan lebih lanjut bahwa sangat mungkin setiap bangunan keraton mempunyai fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut, (1) bangunan Bima adalah balai peperangan, (2) Punta sebagai balai pengadilan, (3) Narayana sebagai balai penghadapan, (4) Madura adalah balai Resepsi, dan (5) Suradipati adalah bangunan persemayaman raja dan keluarganya, kelima bangunan itu yang sering juga disebut dengan Panca Prasadha (Danasasmita 2006: 31).
Tafsiran tentang keraton Pakuwan-Pajajaran juga pernah dilakukan oleh Agus Aris Munandar (1994) berdasarkan perbandingan dengan penataan keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton Kasepuhan menjadi pembanding didasarkan pada argumen bahwa menurut berita tradisi para penguasa Cirebon sebenarnya masih keturunan raja Siliwangi dari Sunda, dan nama keraton Pakuan-Pajajaran juga dikenal dalam kitab Purwaka Caruban Nagari dengan sebutan sang Bima. Artinya kemungkinan besar keraton Pakuwan-Pajajaran dijadikan acuan ketika para penguasa Cirebon mendirikan bangunan keratonnya terutama yang agak tua, yaitu keraton Kasepuhan (Munandar 1994: 100). Sependapat dengan Danasasmita dan Ayatrohaedi bahwa memang kompleks keraton Pakuwan-Pajajaran dahulu terletak di kota Bogor, kompleks tersebut menghadap utara, ke arah alun-alun (buruan), dan di latar belakangnya berdiri Gunung Salak dengan kelima puncaknya. Bangunan paling depan adalah Bima, lalu berturut-turut Punta, Narayana, Madura, dan Suradipati.
Adapun fungsi bangunan tersebut masing-masing sangat mungkin sebagai berikut, (1) Bima dapat dibandingkan dengan bangunan sitinggil di keraton kasepuhan, yaitu sebagai tempat para penjaga dan tempat bersemayamnya sultan ketika melihat aktivitas yang dilaksanakan di alun-laun depan kompleks keraton. Wujud bangunan Bima sangat mungkin tinggi atau berdiri pada lahan yang ditinggikan sebagaimana sitinggil (tanah yang ditinggikan) pada komplek Kasepuhan. (2) Punta adalah gelar bangsawan tinggi, mungkin bangunan ini adalah tempat berkumpulnya para pejabat tinggi kerajaan sebelum diterima oleh raja, sebagaimana bagian keraton Jinem Pangrawit di Kasepuhan yang juga berfungsi sebagai ruang tunggu para tamu yang akan menghadap raja dan mengutarakan terlebih dahulu maksud kedatangannya, (3) Narayana, sangat mungkin sebagai balai tempat pertunjukan kesenian di lingkungan keraton, hal yang sama terdapat di Kasepuhan dinamakan bangsal Pringgondani, (4) Madura, adalah bangunan keraton yang sangat mungkin berfungsi sebagai balai penghadapan, tempat pertemuan antara raja dengan pejabat tinggi kerajaannya dalam mengadakan rapat atau membicarakan berbagai masalah lainnya. Setara dengan Madura adalah bangsal Prabhayaksa di keraton Kasepuhan yang juga berfungsi sebagai balai penghadapan, pertemuan pejabat tinggi dengan sultan, (5) Suradipati adalah bangunan tempat bersemayamnya raja, letaknya paling belakang, paling dekat dengan Gunung Salak dan gunung-gunung lainnya di pedalaman tatar Sunda. Dalam lingkungan keraton Kasepuhan bangunan tempat tinggal raja beserta keluarganya sehari-hari dinamakan Dalem Arum. Adapun tempat bersemayamnya sultan pada waktu terjadi penghadapan agung adalah pada bangunan yang lantainya ditinggikan yang terletak di bagian selatan bangsal Prabhayaksa, dinamakan dengan bangsal Panembahan. Baik Dalem Arum maupun bangsal Panembahan keduanya terletak pada bagian utama keraton, di area paling selatan (Munandar 1994: 100—2).
Demikianlah bahwa akibat dari sedikit ungkapan Poerbatjaraka yang berkenaan dengan data arkeologis, yaitu asal nama Pakuwan-Pajajaran yang diartikan sebagai bangunan keraton yang berjajar. Pernyataan itu lalu dihubungkan dengan data Carita Parahyangan tentang adanya keraton kerajaan Sunda yang disebut Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, telah menjadikan penelisikan arkeologi berkembang untuk melengkapi pemahaman tentang keraton yang berjajar tersebut.
Banyak contoh lainnya yang hanya berupa ”sentilan” saja dari Poerbatjaraka namun dapat dianggap sebagai pemicu selanjutnya bagi penelitian arkeologi. Misalnya tentang kata Minanga Kamwar dalam prasasti Kedukan Bukit (605 S/683 M) menjadi Minanga Kamwa lalu diucapkan Minang Kabau. Tafsir Poerbatjaraka menyatakan bahwa sangat mungkin pada zaman dahulu terdapat tokoh dari Minang Kabau yang berperang, lalu singgah di Malayu (Jambi), lalu terus ke Palembang dengan mendapat kemenangan, akhirnya membuat kota di daerah itu dan dinamakan Sriwijaya (Poerbatjaraka 1952: 35). Apabila benar dugaan Poerbatjaraka tersebut maka daerah Minangkabau di Sumatra Barat berpotensi mempunyai banyak peninggalan arkeologis. Sampai beberapa waktu lamanya tidak pernah diadakan penelisikan arkeologi secara intensif di wilayah tersebut, namun dalam tahun-tahun belakangan ini ketika diadakan penelitian arkeologi, dijumpai banyak tinggalan arkeologis baik yang berupa struktur bangunan, parit-parit yang panjang, pecahan arca dan lain-lain. Juga tafsiran Poerbatjaraka bahwa daerah Salatiga merupakan daerah penting karena disebutkan dalam prasasti Plumpungan yang telah disinggung di bagian terdahulu, selayaknya patut ditindaklanjuti dalam penelitian arkeologi. Setidaknya menurut laporan penduduk setempat belakangan ini, di beberapa tempat kuburan desa di wilayah Salatiga juga dijumpai arca-arca kecil dari emas.
IV
Dalam kitab Calon Arang yang dikaji oleh Poerbatjaraka juga terdapat data arkeologi yang dapat dijadikan dasar bagi penelitian di lapangan. Dalam naskah itu diuraikan bahwa pertapaan dapat didirikan pada suatu tempat bekas kuburan atau pembakaran mayat (ksetra). Lahan ksetra Gandamayu setelah Calon Arang berhasil dikalahkan oleh pendeta Bharadah disucikan terlebih dahulu, lalu untuk suatu pertapaan pendeta agung yang disertai murid-muridnya, maka di lingkungan pertapaan itu didirikan pendapa-pendapa untuk tamu dan tempat tinggal, bangunan persajian serta gapura yang sudah tentu bersambung dengan pagar kelilingnya berupa tanaman jajaran pohon sirih yang membatasi lahan pertapaan. Pohon-pohon dan bunga-bungaan pun ditanam di lingkungan pertapaan dan diuraikan secara rinci, yaitu angsoka, andul, surastri, kemuning, cempaka, angsana, jering (jengkol), nagasari, sedangkan tanaman perdu lainnya berupa bunga melati, kuranta, gambir, kembang sepatu, wungatali, pacarcina, bunga telang, mayana, dan tidak ketinggalan pandan kebun yang wangi (Poerbatjaraka 1975: 22).
Data tentang gambaran suatu pertapaan tersebut sangat berharga bagi pengembangan kajian arkeologi Hindu-Buddha. Deskripsi tentang kompleks tempat tinggal kaum agamawan sangat terbatas diuraikan dalam sumber tertulis, selain dalam kakawin Arjunawijaya yang telah dibahas oleh S.Soepomo (1977), gambaran tentang tempat bermukim kaum agamawan hanya dijumpai dalam kitab Calon Arang yang dikaji Poerbatjaraka tersebut. Dapat disimpulkan bahwa apabila dalam Arjunawijaya yang diuraikan adalah suatu kompleks luas berupa pemukiman keagamaan yang disebut kadewaguruan dan mandala (Soepomo 1977: 67—8), agaknya uraian dalam kitab Calon Arang merupakan pertapaan yang tidak terlalu luas karena dihuni secara terbatas oleh Mpu Bharadah dan beberapa muridnya saja.
Gambaran tentang pertapaan dalam kitab Calon Arang sebenarnya sangat mirip dengan keadaan Candi Kotes (Papoh) di Blitar. Candi Kotes sekarang hanya menyisakan batur dari susunan balok batu dan beberapa batu umpak bagian alas tiang, sedangkan tiang-tiang dan atap bangunan sudah tiada, dapat dipastikan dahulu terbuat dari bahan yang cepat lapuk (kayu, bambu, ijuk, dan lainnya yang sejenis). Selain itu di bagian depan batur tersebut terdapat batur lain yang lebih kecil namun lebih tinggi dari batur pertama, di permukaan batur kedua terdapat dua altar persajian kecil, dan pedupaan yang berbentuk candi kecil. Jelaslah bahwa batur kedua merupakan bangunan persajian dan persembahan kepada dewa. Kemungkinan besar di masa silam terdapat pula gapura, namun sekarang telah rusak. Karena adanya kemiripan yang sangat dekat dengan uraian pertapaan dalam kitab Calon Arang, maka kiranya dapat ditafsirkan bahwa Candi Kotes dahulu merupakan kompleks pertapaan pula. Begitupun penyebutan bermacam tanaman yang ada di lingkungan pertapaan, agaknya dapat dijadikan pegangan apabila para arkeolog hendak merekonstruksi macam tumbuhan dalam taman pada waktu itu, sebab sebagian besar tanam-tanaman yang disebutkan masih dapat dikenali hingga sekarang.
Hal yang menarik lainnya dalam kitab Calon Arang hasil kajian Poerbatjaraka, dinyatakan bahwa dalam masa pemerintahan raja Airlangga, banyak orang asing dari luar Jawa yang datang ke Kadiri untuk menghambakan diri kepada Airlangga. Juga diuraikan banyak daerah dari pulau lain yang mengirimkan utusannya untuk mempersembahkan upeti. Orang-orang dari seberang yang datang antara lain dari Palembang, Jambi, Malaka, Tumasik, Patani, Pahang, Siam, Campa, Cina, Koci, Keling, Tatar, Pego, Kedah, Kutawaringin, Kute, Bangka, Sunda, Madura, Kangeyan, Makasar, Goron, Wandan, Peleke, Maluku, Bolo, Timor, Dompo, Bima, Sumbawa, Sasak (Poerbatjaraka 1975: 50). Tidak disebutkannya Bali dalam daftar tersebut memang sesuai dengan konteksnya bahwa Bali memang tidak tunduk kepada Jawa dalam masa pemerintahan Airlangga. Daftar daerah di luar tlatah asli kerajaan Airlangga yaitu tanah Jawa bagian timur menunjukkan bahwa keagungan Airlangga sebagai raja diakui pula oleh wilayah lain di Nusantara. Uraian perihal daerah yang mengirimkan upeti tersebut mirip dengan yang disusun oleh Mpu Prapanca dalam Nagarakartagamanya dalam masa Majapahit (abad ke-14 M), tetapi daerah yang disebutkan dalam kitab Calon Arang jauh lebih sedikit. Beberapa kajian di lingkungan arkeologi belakangan ini memang menyimpulkan bahwa Airlangga ialah seorang raja besar di Nusantara, setara dengan raja-raja besar lainnya di wilayah Asia Tenggara dalam zamannya.
Kajian Poerbatjaraka lainnya yang juga mengandung data arkeologi dan dapat dijadikan titik tolak penelitian di bidang arkeologi adalah kajiannya tentang Cerita Panji. Dalam uraian Cerita Panji terdapat beberapa data arkeologis yang belum ditindaklanjuti dengan baik oleh para arkeolog. Misalnya dalam cerita Angron Akung dinyatakan bahwa di sisi barat alun-alun Jenggala terdapat batu rata yang besar, batu tersebut amat keramat tetapi juga angker dan berbahaya, siapa yang menyentuhnya pasti mati. (Poerbatjaraka 1968: 124). Bagian selanjutnya dari uraian itu tidak terlalu penting karena tidak berkaitan dengan kajian arkeologi.
Apabila diperhatikan tata letak pusat kota dalam masa awal perkembangan Islam di Jawa, maka terdapat hal yang dapat didiskusikan. Pusat kota adalah alun-alun yang berada di tengah, di selatan alun-alun berdiri keraton atau tempat tinggal penguasa, di timur terdapat bangunan-bangunan penegakkan hukum, di utara terdapat pasar, dan di barat berdirilah masjid. Data arkeologi Islam di Jawa menunjukan bahwa pada awalnya mesjid-mesjid kuna didirikan di bekas lahan, atau menutup lahan bangunan suci masa sebelumnya dari era Hindu-Buddha. Misalnya masjid kuna Mantingan dibangun di situs masa Hindu-Buddha, demikian juga halnya dengan masjid kuna Sendang Duwur dan mesjid menara Kudus, karena anasir kehinduan masih nampak secara nyata.
Maka bukan tidak mungkin bahwa kota-kota dalam masa Hindu-Buddha di Jawa dalam masa praIslam mempunyai penataan yang berpusatkan pada alun-alun, di selatannya berdiri kedaton, kadipaten tempat tinggal penguasa wilayah, di timur adalah balai peradilan, di utara pasar, dan di barat alun-alun berdiri candi atau bangunan suci lainnya yang dikeramatkan. Ketika Islam mulai berkembang di tanah Jawa, bangunan yang bersifat Hindu-Buddha di sisi barat alun-alun itu lalu digantikan kedudukannya dengan masjid. Jadi kedudukan bangunan suci atau tempat yang dikeramatkan dari masa Hindu-Buddha digantikan dengan bangunan masjid, sebagaimana yang terjadi di beberapa tempat di Jawa.
Sementara itu dalam kisah Malat pupuh 8 terdapat uraian tentang pasanggrahan Pranaraga, suatu tempat menyepi sementara yang didiami oleh Panji dan kawan-kawannya. Untuk membangun pasanggrahan itu Panji membawa tukang kayu dan batu, mereka ditugaskan untuk mendirikan gedung-gedung baru, begitupun papan-papan dinding dan penyekat ruang digambari dengan cerita Pandawa-Jaya (Poerbatjaraka 1968: 302). Dalam hal ini arkeologi juga mendapat data lagi untuk melakukan penelitian lapangan. Bahwa terdapat juga bangunan-bangunan profan selain keraton yang dihuni sementara oleh raja atau kaum kerabatnya. Bangunan itu sangat mungkin jauh dari keramaian di lingkungan panorama yang indah di lereng gunung atau di tepian hutan. Karena itu apabila dalam penelitian arkeologi didapatkan situs yang terletak di lereng-lereng gunung tidak selalu peninggalan bangunan suci seperti candi, mungkin juga merupakan bangunan profan atau pasanggrahan sebagaimana yang disebutkan dalam Malat.
Dalam Hikayat Panji Kuda Semirang diuraikan bahwa Panji dan kawan-kawannya sampai di kaki Gunung Danuraja yang sangat angker di wilayah Mataun. Panji berkehendak untuk mendaki ke puncaknya karena di sana terdapat orang suci yang telah bertapa selama 400 tahun. Kepada orang suci itu Panji hendak bertanya tentang nasib Candrakirana. Gunung Danuraja itu sangat berbahaya, barangsiapa yang berani mencapai puncaknya akan diserang oleh hujan, angin topan, dan kabut tebal. Inu dan pengiringnya mendaki gunung itu dengan tidak gentar, karena Inu merasa dirinya masih dilindungi dewa-dewa, sampailah ia dan kawan-kawannya di puncaknya. Pertapa suci yang tinggal di puncak Gunung Danuraja itu ialah Cakcasena, ia adalah ayah dari Cakcakuwaca yang merupakan leluhur Hanuman. Demikianlah akhirnya Panji dan kawan-kawan dapat diterima oleh Caksasena bahkan tinggal berguru beberapa lama di gunung tersebut. Cakcasena meramalkan bahwa Anggarmayang (Martalangu) dan Tjandrakirana masih hidup, hanya belum waktunya ditemui (Poerbatjaraka 1968: 25—6).
Uraian tentang keangkeran Gunung Danuraja, fenomena alam yang ditemui oleh para pendakinya, serta pertapaan Caksasena yang merupakan leluhur Hanuman, sang raja monyet agaknya mengacu kepada Gunung Penanggungan di Jawa Timur. Di Gunung Penanggungan didapatkan sekitar 80 kepurbakalaan baik yang berupa punden berundak, goa pertapaan, petirthaan arca lepas, deretan anak tangga mendaki, sisa batur, dan ribuan pecahan tembikar lainnya. Gunung tersebut juga dikenal sebagai salah satu karsyan yang terkenal dalam zaman Majapahit, dinamakan karsyan Pawitra. Karsyan tersebut sangat angker dan dikeramatkan karena dianggap sebagai puncak Mahameru yang dipindahkan para dewa dari Jambhudwipa ke Tanah Jawa, demikian tutur kitab Tantu Panggelaran.
Orang-orang yang mendaki Gunung Penanggungan di waktu sekarang pun akan selalu diterpa angin yang kencang dan puncak gunung tersebut kerapkali ditutupi kabut tebal. Hal itu terjadi karena Gunung Penanggungan merupakan puncak tertinggi satu-satunya di wilayah Mojokerto selatan, jadi gunung tersebut akan mendapat terpaan langsung angin darat pada waktu malam ataupun angin laut pada waktu siang. Disebabkan Gunung Penanggungan merupakan fenomena geografis tertinggi di wilayah itu maka awan dan uap air seringkali berkumpul di wilayah puncaknya, baik pada musim kemarau apalagi di waktu musim hujan, air hujan akan turun dengan derasnya bercampur dengan deru angin. Demikianlah uraian kondisi alam Gunung Danuraja sangat dekat dengan keadaan alam sebenarnya di Gunung Penanggungan.
Hal yang menarik adalah bahwa di lereng bukit Bekel, salah satu puncak sisi barat laut puncak Penanggungan, terdapat kepurbakalaan yang berupa punden berundak besar yang dindingnya dihias relief kisah Panji, di sebelahnya terdapat celah bukit alami dibentuk menjadi goa pertapaan yang dilengkapi dengan gapuranya. Bangunan kuna itu dalam kajian arkeologi Hindu-Buddha di Gunung Penanggungan dinamakan Kepurbakalaan LXV, sedangkan penduduk setempat menamakannya dengan Candi Kendalisada. Kata Kendalisada dalam khasanah cerita pewayangan Jawa, adalah nama kerajaannya Hanuman. Dalam hal ini mungkin saja terdapat hubungan gagasan antara pertapa Cakcasena sang leluhur Hanuman yang bermukim di Gunung Danuraja dengan Kepurbakalaan LXV yang dinamakan juga Candi Kendalisada di situs Gunung Penanggungan. Mungkin saja penyusun Hikayat Panji Kuda Semirang telah mengetahui perihal karsyan Pawitra di Penanggungan dengan Candi Kendalisadanya. Kajian arkeologi yang lebih mendalam mengenai relief kisah Panji yang dipahatkan di dinding Candi Kendalisada mungkin dapat menjawab permasalahan tersebut.
V
Demikianlah bahwa sebenarnya Poerbatjaraka tidak secara langsung melakukan kajian arkeologi, karena sebagaimana diketahui Pak Poerba adalah ahli bahasa dan sastra Jawa kuna. Didasarkan kepada kajiannya itulah mau tidak mau penelisikan Poerbatjaraka menyinggung atau bahkan berkenaan dengan permasalahan arkeologi. Kajian yang sarat dengan permasalahan arkeologi dan epigrafi adalah disertasinya sendiri. Walaupun arca-arca Agastya sebagai benda arkeologi tidak dipergunakan sebagai data dalam kajiannya, namun pembahasan Poerbatjaraka dalam disertasinya berkenaan dengan salah satu permasalahan arkeologi Hindu-Buddha di Indonesia.
Berkat kajian Poerbatjaraka itulah maka tafsiran yang telah lama mengendap bahwa arca orang tua berperut buncit berjanggut, bertangan dua, dan ditempatkan dalam relung selatan candi-candi Hindu di Jawa sebagai Mahaguru atau Siva Mahaguru terpaksa harus disingkirkan. Arca itu bukan Mahaguru, melainkan Agastya salah seorang saptarsi (tujuh pendeta agung murid kesayangan Siva).
Kajian Poerbatjaraka tentang prasasti (epigrafi) sebagai cabang dari ilmu arkeologi jelas mendukung untuk menjelaskan masalah sejarah kuna Indonesia era Hindu-Buddha. Pembacaan dan tafsiran atas beberapa prasasti masa awal zaman Hindu-Buddha dijadikan dasar bagi penulisan buku sejarah kuna Riwayat Indonesia I yang metodenya berbeda dengan penulisan sejarah kuna yang telah disusun oleh para sarjana Belanda sebelumnya. Dalam buku Riwayat Indonesia I data prasasti yang dipakai sebagai dasar penulisan dipaparkan terlebih dahulu, baru kemudian dibahas dan diberikan tafsir sejarahnya. Sedangkan para penulis sejarah kuna orang Belanda hanya merangkumkan isi prasasti-prasasti itu dan dibuat suatu kisah sejarah yang kadang-kadang terlalu jauh menyimpang dari isi prasastinya sendiri.
Adapun kajian Poerbatjaraka terhadap sejumlah naskah sebagai sumber tertulis telah menyediakan bermacam masalah yang selayaknya harus dipecahkan oleh para ahli arkeologi. “Sentilan-sentilan” Poerbatjaraka perihal permasalahan arkeologi dalam kajian naskahnya bukanlah sesuatu yang dianggap sambil lalu saja, namun jika para arkeolog itu cermat dan memahami permasalahan yang dimaksudkan, maka dapat ditindaklanjuti dengan penelitian arkeologi sehingga pemahaman tentang kemasalaluan Indonesia menjadi lebih luas. Pesan Poerbatjaraka tentang jangan terlalu mengagungkan masa lalu bangsa Indonesia adalah tepat, sebab masyarakat Indonesia hidup dalam masa sekarang yang penuh dengan berbagai pengaruh kebudayaan luar. Akhirnya Pak Poerba juga menganjurkan untuk memilih yang baik dari masa lalu agar dapat menjadi teladan kehidupan masa kini, di samping itu dapat terima juga pengaruh kebudayaan luar yang bersifat positif demi kemajuan bangsa Indonesia sampai hari kemudian. Pesan itu sepantasnya harus diingat terus oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam zaman-zaman yang berbeda.
Pustaka AcuanAYATROHAEDI, 1978, “Pajajaran atau Sunda”, dalam Majalah Arkeologi. Th 1 No.4. Maret. Jakarta: Jurusan Arkeologi, Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Halaman 46—54.
BOECHARI, 1964, “Prof.Dr.Ng.Poerbatjaraka Ahli Epigrafi Perintis Bangsa Indonesia”, dalam Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia. Nomor Persembahan Kepada Prof.Dr.R.M.Ng.Poerbatjaraka Berhubungan dengan Ulang Tahun Beliau ke-80 dari Para Murid Beliau. Juni, Jilid II, Nomor 2. Djakarta: Bhratara. Halaman 119—130.
DANASASMITA, SALEH, 2006, Mencari Gerbang Pakuan dan Kajian lainnya Mengenai Budaya Sunda. Bandung: Pusat Studi Sunda.
KERN, H., 1917, “Over den invloed van den Indische, Arabische en Europeesche beschaving op de volken van den Indischen Archipel. VG 6: 11—35.
KROM, N.J., 1933, Hindoe-Javaanche Geschiedenis. s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
MIHARJA, ACHDIAT K., (Penyunting) 1986, Polemik Kebudayaan. Cetakan ke-4
Jakarta: Pustaka Jaya.
MUNANDAR, AGUS ARIS, 1994, “Penataan Wilayah pada Masa Kerajaan Sunda”, dalam Berkala Arkeologi Tahun XIV Edisi Khusus: Evaluasi Data dan Interpretasi Baru Sejarah Indonesia Kuna (Dalam Rangka Purna Bhakti Drs.M.M.Soekarto Karto Atmodjo), Yogyakarta, 23—24 Maret 1994. Yogyakarta: Balai Arkeologi.
POERBATJARAKA, R.M.Ng, 1921, “De Batoe Toelis bij Buitenzorg” , TBG. Deel LIX: 380—418.
-------------------------, 1951, Riwajat Indonesia Djilid I. Djakarta: Jajasan Pembangunan.
-------------------------, 1968, Tjeritera Pandji Dalam Perbandingan. Diterdjemahkan oleh Zuber Usman dan H.B.Jassin. Djakarta: P.T.Gunung Agung.
-------------------------, 1975, Calon Arang Si Janda dari Girah & Nirarthaprakreta. Diterjemahkan oleh Soewito Santoso. Jakarta: Balai Pustaka.
-------------------------, 1992, Agastya di Nusantara. (Seri Terjemahan KITLV-LIPI). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
SANTIKO, HARIANI, 1989, ”Waprakeswara: Tempat Bersaji Pemeluk Agama Veda?”, dalam Amerta Berkala Arkeologi No.11. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Halaman 1--8.
SOEPOMO, S., 1977, Arjunawijaya: A Kakawin of Mpu Tantular. Vol.I & II. The Hague: Martinus Nijhoff.
STUTTERHEIM, W.F., 1934, “De Leidsche Bhairawa van Candi B Singasari”, TBG LXXIV: 441—476.
SUTAARGA, MOH.AMIR, 1965, Prabu Siliwangi atau Ratu Purana Prebu Guru Dewataprana Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakwan Pajajaran 1474—1513. Bandung: Duta Rakjat.
VOGEL, J.PH., “The Yupa Inscriptions of King Mulawarman from Koetei (East Borneo)”, BKI 74: 167—232.
WIBOWO, A.S., 1976, “Riwayat Penyelidikan Prasasti di Indonesia”, dalam 50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional 1913—1963. Jakarta: Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional. Halaman 63—105.